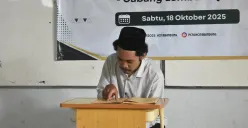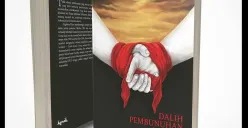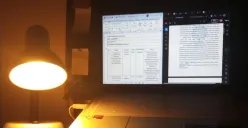Konflik antara Israel dan Palestina kembali mengoyak nurani dunia. Mata seluruh dunia tertuju pada konflik yang telah menelan ratusan ribu korban sipil, kehancuran infrastuktur dan penderitaan tanpa akhir.
Gerakan solidaritas datang dari berbagai penjuru dunia, termasuk Indonesia. Salah satu bentuk dukungan yang disuarakan adalah Gerakan boikot terhadap produk dan perusahaan yang terafiliasi dengan aggressor.
Aksi ini diperkuat dengan keluarnya fatwa MUI nomor 83 tahun 2023 tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuanga Palestina. Melalui CNBC Indonesia Roy Nicholas Mandey (Ketua Umum Aprindo), telah melaporkan bahwa pada tahun 2023 produk fast moving dan consumer goods turun hingga 40% .
Sehingga munculah pertanyaan krusial: Apakah boikot benar-benar efektif secara ekonomi dan bermakna secara sosial? Atau justru berisiko menciptakan dampak domestik yang tak diinginkan?
Solidaritas Kemanusiaan dalam Bingkai Keilmuan
Menurut (Garrett, 1987), boikot adalah penolakan kolektif untuk berbisnis dengan individual atau perusahaan terhadap tindakan atau praktik tertentu yang dilakukan oleh individul atau perusahaan tertentu dengan tujuan mendapatkan konsesi atau menyampaikan keluhan terhadap tinakan atau praktik yang dilakukan oleh indvidu atau perusahaan tersebut.
Boikot sebagai bentuk aksi sosial dapat dianalisis melalui pendekatan teori Etika Global dari (Thomas Pogge, 2005) yang menyatakan bahwa masyarakat global memiliki tanggung jawab moral untuk tidak berkontribusi, secara langsung maupun tidak langsung, terhadap sistem ketidakadilan.
Dalam konteks ini, memilih untuk tidak membeli produk dari entitas yang mendukung agresi menjadi praktik etis konsumen (ethical consumption), yang memperkuat nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab sebagaimana terkandung dalam Pancasila.
Gerakan boikot juga mencerminkan prinsip nonviolent resistance (Gene Sharp, 1973), di mana tekanan moral dan ekonomi menjadi sarana menggoyahkan kebijakan atau kekuatan yang tidak adil. Ini merupakan bentuk perjuangan tanpa senjata, namun tetap kuat secara politik dan sosial.
Dampak Ekomoni: Tekanan terhadap Global , Peluang bagi Lokal
Tulisan ini merupakan pendapat penulis dengan perspektif ekonomi terhadap aksi ini tanpa mengesampingkan nilai-nilai kemanusaiaan. Dalam prespektif ekonomi mikro, aksi ini menciptakan shifting consumer demand.
Ketika terjadinya penurunan permintaan terhadap produk asing yang diduga terafiliasi, ini membuka peluang kenaikan permintaan bagi produk lokal sebagai produk pengganti. Hal ini selaras dengan teori elastisitas permintaan: jika produk yang diboikot memiliki subtitusi yang kompetitif, maka konsumen akan beralih.
Beberapa laporan menyebutkan bahwa brand multinasional yang diduga terafiliasi mengalami penurunan signifikan di Indonesia dan negara-negara mayoritas muslim. Peluang berpindahnya pada penggunaan produk lokal tetap harus diwaspadai.
Apakah ini diikuti dengan tidak turunnya daya beli masyarakat akibat dampak yang ditimbulkan pada pelaku usaha lokal yang merupakan mitra dari brand tersebut. Jika ternyata pada kenyataannya permintaan masyarakat terhadap suatu barang menurun akibat turunnya daya beli. Maka kesempatan shifting consumer demand ini tidak akan terjadi sepenuhnya.
Namun di sisi lain , jika UMKM lokal siap menangkap peluang baik dari shifting ini dengan penyediaan produk yang kompetitif dan berkualitas. Ini akan menjadi momentum bangkitnya produk lokal. Dengan tetap terjaganya jumlah permintaan di pasar dan didorong oleh narasi kemanusiaan, konsumen akan beralih dengan sukarela kepada produk-produk yang disediakan oleh UMKM.
Hal ini akan sejalan dengan konteks ekonomi kerakyatan, di mana kekuatan ekonomi diarahkan untuk mendukung produsen kecil dan menengah yang berperan dalam pembangunan. Sehingga diharapkan perekonomian secara makro dapat tetap dapat tumbuh.
Walaupun pada kenyataanya pertumbuhan yang terjadi pada sektor mikro belum dapat mengimbangi penurunan yang terjadi secara nasional pada beberapa sektor bisnis. Ini dapat dijadikan bibit awal untuk tetap menjaga pertumbuhan ekonomi nasional.
Agar dapat menghadapi dampak dari aksi ini, perlu adanya strategi holistik yang melibatkan semua elemen yang terlibat dalam perekonomian secara makro maupun mikro. Pemerintah diharapkan dapat memberikan stimulus ekonomi yang diakibatkan naiknya angka penggaguran agar daya beli dan permintaan masyarakat dapat tetap terjaga.
Pada sektor mikro, pelaku usaha harus cerdas dalam mengelola ongkos produksi dengan tetap mempertahankan kualitas agar dapat menciptakan kepuasan konsumen dan pembelian berulang.
Selain itu ini dapat menjadi momentum bagi Indonesia untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor. Dengan menguatnya produk UMKM dan optimalisasi hilirasi industri, sehingga sumber daya yang dimiliki oleh negara ini dapat dikelola dan dirasakan kebermanfaatannya oleh kita sendiri.

Ketahanan ekonomi dalam negeri pun akan semakin kuat, terutama jika didukung oleh kebijakan yang berpihak pada produksi lokal, insentif bagi pelaku usaha kecil, dan penguatan ekosistem industri nasional.
Momentum ini juga mendorong munculnya kesadaran kolektif masyarakat untuk lebih memilih produk dalam negeri sebagai bentuk nyata bela negara di bidang ekonomi. Dengan demikian, krisis global akibat konflik perang dapat direspons secara strategis, tidak hanya sebagai tantangan, tetapi juga sebagai peluang untuk membangun kemandirian dan daya saing bangsa.
Hasil dari strategi dan kebijakan yang dibuat untuk menghadapi kondisi ini memang tidak dapat terlihat secara instan. Aksi boikot memberikan dampak yang cukup masif, namun respon terhadap dampak yang terjadi msih terkesan lambat dan belum menunjukkan dampak yang signifikan.
Namun dengan pemahaman dan kesamaan tujuan, semoga hal tersebut menjadi cikal bakal dari bangkitnya perekonomian Indonesia dan perdamaian dunia.
Dampak Sosial: Menguatkan Solidaritas, Merawat persatuan
Gerakan boikot menimbulkan gelombang solidaritas sosial yang kuat. Penyebaran yang dilakukan melalui media sosial menjadi alat penyebaran informasi dan kampanye. Namun hal ini menjadi seperti dua sisi mata uang, dampak sosial itu uga dapat menciptakan polarisasi.
Sebagian masyarakat mendukung penuh gerakan ini sebagai bentuk bela Palestina, sementara sebagaian lain mengkhawatirkan terhadap ekonomi lokal dan khawatir pada bisa informasi. Sehingga peran penting literasi digital dan kedewasaan sosial diperlukan untuk menghindari konflik horizontal.
Secara sosiologis, fenomena ini bisa dibaca melalui teori aksi sosial Max Weber, bahwa tindakan sosial bukan hanya soal hasil, tetapi juga soal nilai yang mendasarinya. Aksi boikot menjadi bentuk manifestasi nilai—yakni kepedulian terhadap keadilan dan kemanusiaan—yang perlu dijaga agar tidak disalahartikan sebagai bentuk intoleransi atau permusuhan buta.
Boikot sebagai Jalan Tengah Kemanusiaan
Aksi boikot terhadap entitas yang mendukung penjajahan adalah hak moral sekaligus bentuk tanggung jawab sosial. Namun, gerakan ini perlu dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, kejelasan informasi, dan orientasi pada solusi.
Boikot bukan sekadar menolak membeli, tetapi membangun kesadaran bersama bahwa kita tidak boleh menjadi bagian dari sistem penindasan. Dengan mengedepankan prinsip kemanusiaan, kedaulatan ekonomi, dan kesatuan bangsa, gerakan ini bisa menjadi momentum edukatif dan transformatif.
Sebagai bangsa, kita perlu menjadikan konflik di luar negeri sebagai cermin untuk memperkuat keadaban di dalam negeri. Aksi ini dapat dimulai dari diri sendiri dengan menjadi menjadi teladan yang menjunjung nilai, menjaga persatuan, serta berpihak pada kemanusiaan dalam laku nyata dan suara kita sehari-hari. (*)