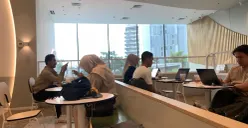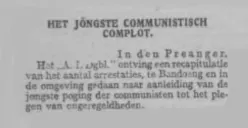AYOBANDUNG.ID - Menjelang waktu asar, Abah Widi tampak bersiap nyajen, sebuah ritual ibadat yang masih dilakukan para penganut kepercayaan Sunda Wiwitan di Kampung Adat Cireundeu, Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi.
Sesepuh berusia 63 tahun itu duduk di depan warungnya, tepat di bawah bangunan Sekolah Dasar Negeri Cirendeu. Dengan iket yang melekat di kepala, ia bercerita dengan ringan tentang kedekatan antara singkong dan kehidupan warga, yang sejak lama menjadikannya simbol kemandirian dan ketahanan pangan.
Kampung yang dinamai dari pohon reundeu itu telah mengikat tradisi dan ketahanan pangan dalam satu napas. Sejak 1918, kata Abah Widi, singkong menjadi simbol perlawanan terhadap penjajah sekaligus penanda kemandirian masyarakat adat. Saat penjajah merebut lahan dan hasil bumi, warga beralih dari beras ke singkong sebagai bentuk bertahan hidup.

Selain mudah tumbuh di berbagai kondisi cuaca, singkong bagi mereka adalah warisan leluhur yang menyimpan ajaran hidup sederhana, merawat alam, dan berbagi sesama manusia.
“Penjajah kan dulu ambil hasil bumi dan lahan, supaya pribumi kelaparan dan tak bisa menggarap lahan sendiri. Makanya sesepuh Cirendeu dulu memberikan pemahaman tentang cara bertahan hidup yang tidak bergantung pada beras,” kata Abah Widi.
“Sejak 1918 warga di sini mulai beralih makanan pokok dari beras ke hasil pertaninan yang lain, seperti singkong, ganyol, anjeli, jagung, hingga talas,” Abah Widi menambahkan.
Secara filosofis, singkong—atau sampeu dalam bahasa Sunda—punya makna yang dalam. Bagi Abah Widi, istilah sampeu berasal dari kata sampeureun, yang berarti “didatangi.” Ia menyebut, secara ekonomi tanaman ini tak menyisakan limbah karena semua bagian tanaman bermanfaat.
“Kalau diselami secara bahasa, pare (padi) itu kan parab anu rea (makanan yang banyak), nah kalau sampeu, ya sampeureun harus didatangi,” ucapnya.

Rasi, Warisan Leluhur yang Tak Pernah Punah
Sambil mengisap rokok lewat cangklongnya, Abah Widi menegaskan bahwa rasi—beras singkong—adalah warisan leluhur yang harus dilestarikan tanpa batas waktu. Ia menyadari perubahan zaman membawa tantangan baru bagi generasi muda, namun bukan berarti tradisi harus hilang. Tradisi ini terus dijaga oleh sekitar 60 kepala keluarga di kampung itu, yang menurunkannya dari generasi ke generasi sebagai wujud swasembada pangan yang khas dan mandiri.
Bagi warga Cirendeu, modernitas bukan ancaman. Mereka tidak menolak teknologi, pendidikan tinggi, atau profesi baru, asalkan tetap berakar pada nilai leluhur.
“Cireundeu secara geografis bisa dibilang kampung adat yang ada di tengah kota. Gempuran teknologi dan pendidikan itu ada. Tapi yang jelas zaman sama saja dari dulu juga, yang mengubah ya manusia. Intinya jangan lupa bahasa ibu dan sejarah,” tuturnya.
Dalam keseharian, masyarakat Cirendeu menjaga hubungan dengan alam melalui prinsip-prinsip lama: mipit kudu amit, ngala kudu bebeja. Pepatah itu menandakan rasa hormat kepada alam yang menyediakan kehidupan. Kata “pamali” pun menjadi pagar moral untuk menahan keserakahan manusia.
Tiga kawasan hutan dijaga sebagai bagian dari keseimbangan hidup: Hutan Larangan untuk penyimpanan air, Hutan Tutupan untuk reboisasi, dan Hutan Baladahan sebagai lahan berkebun. Semua dikelola dengan kearifan dan kesadaran ekologis.
“Teu Boga Sawah Asal Boga Pare, Teu Boga Pare Asal Boga Beas, Teu Boga Beas Asal Bisa Nyangu, Teu Nyangu Asal Dahar, Teu Dahar Asal Kuat,” kata Abah Widi.
“Tidak Punya Sawah Asal Punya Beras, Tidak Punya Beras Asal Bisa Menanak Nasi, Tidak Punya Nasi Asal Makan, Tidak Makan Asal Kuat,” begitu bila diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia.
Pepatah itu bukan sekadar ucapan, tetapi ruh kehidupan di Cirendeu. Gotong royong menjadi napas sosial mereka, sementara perempuan memegang peran penting dalam mengolah hasil tani menjadi sumber ekonomi keluarga.
“Gotong royong adalah hal yang lumrah, ditambah peran perempuan di sini yang belajar mengolah hasil pertaninan hingga punya nilai ekonomis sangat berdampak pada ketahanan pangan,” kata Abah Widi.

Singkong, Benteng Alami Melawan Krisis Iklim
Di tengah ancaman perubahan iklim, rasi menjadi simbol ketangguhan lokal. Ketika banyak wilayah khawatir akan gagal panen atau naiknya harga beras, warga Cirendeu tetap tenang. Singkong yang diolah menjadi tepung kasar sebelum dinanak seakan tak tergoyahkan oleh cuaca ekstrem.
“Warga adat Cireundeu mah seperti sudah punya naluri kalau berbelanja atau membeli makanan di luar yang terbuat dari beras. Apalagi di sini mah enggak ada yang namanya kasus beras plastik. Kadang saya mah suka bertanya, kenapa negeri yang tanahnya subur aja masih impor beras dari luar,” ucapnya.
Ketahanan pangan Cirendeu bukan hanya soal swasembada, tetapi juga empati.
“Kami memang tidak terpengaruh soal naiknya harga beras, tapi Abah mah sok punya rasa peduli terhadap orang-orang yang kelaparan, tidak bisa beli beras, anaknya banyak. Karena yang disentuh itu rasa terhadap manusia,” katanya.
Keanekaragaman hayati juga menjadi bagian dari kekuatan adaptif mereka. Selain singkong, warga menanam jagung, sorgum, kacang tanah, dan anjeli dengan sistem tumpang sari.
“Tantangan serius adalah mengubah pola pikir. Kadang secara batin saya merasa kasihan terhadap orang-orang yang masih kelaparan karena tak bisa makan nasi. Padahal Cireundeu 107 tahun tidak makan nasi beras,” Abah Widi menjelaskan.
Baginya, ketergantungan pada beras adalah akar persoalan. Cireundeu telah membuktikan hidup tanpa nasi bukanlah kekurangan, tetapi kebebasan.
“Banyak yang melakukan penelitian ke sini, dan bahkan ada juga yang mencoba membantah tradisi makan singkong karena curah hujan tinggi. Tapi ya kami terbuka terhadap dunia luar, asal tidak mengubah tradisi kami. Saya mah syukur-syukur ada Cireundeu-Cireundeu yang lain malahan,” ujarnya.

Bersinergi dengan Pemerintah, Bukan Menolak Dunia Luar
Meski memegang teguh adat, warga Cirendeu tidak menutup diri dari kebijakan pemerintah. Mereka justru membangun sinergi dalam berbagai bidang, termasuk pengembangan UMKM olahan singkong.
“Di sini ada RT, RW ya layaknya tata kelola pemerintahan. Kami tidak menolak, bahkan berdampingan. Pemerintah kota juga beberapa kali membantu kegiatan UMKM olahan singkong dengan memberikan alat penggiling,” ujarnya.
Hubungan harmonis dengan pemerintah menjadi cermin sikap terbuka masyarakat adat. Mereka memilih berdialog daripada menolak.
“Abah ada cerita dulu waktu kecil pernah dipoyok (diolok-olok) karena dianggap aneh makan nasi singkong oleh teman sebaya. Setelah ditelaah ya itu wajar dan kami maklum. Sebetulnya juga tidak sedikit warga adat juga mengalami hal sama, tapi ya balik lagi, maklum,” tutur Abah Widi.
Abah menyadari stigma semacam itu bisa memengaruhi generasi muda. Namun, Cirendeu memilih membangun narasi positif: bahwa perbedaan bukan ancaman, melainkan kekayaan.

Budaya Bukan Sekadar Bisnis
Kini, olahan singkong dari Cirendeu telah memiliki nilai ekonomi. Namun, bagi Abah Widi, inti dari semua ini bukan keuntungan materi, melainkan pelestarian budaya.
“Di sini ada UMKM pangan singkong yang dikelola ibu-ibu. Kalau ditanya peluang bisnis memang besar dan ada pasarnya. Tapi, kami memegang prinsip ini adalah salah satu pelestarian budaya, untung atau rugi itu hal kesekian,” ucapnya.
Sebelum berpamitan, Abah Widi yang masih duduk di dekat warungnya menawarkan sepiring rasi hangat dan memperlihatkan tepung singkong hasil olahan warga. Teksturnya lembut, rasanya alami.
“Memang lebih enak kalau pakai lauk, biar ada rasanya,” katanya sambil tertawa kecil, menutup perjumpaan sore itu—sebuah tawa yang menyiratkan kebanggaan pada kemandirian yang lahir dari bumi sendiri.