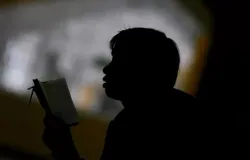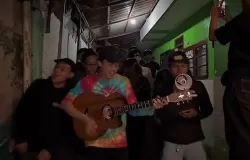Di era perubahan yang kian cepat, dunia kerja tidak hanya menuntut kecerdasan akademis atau keterampilan teknis. Kemampuan untuk terus belajar, melepas kebiasaan lama, dan beradaptasi dengan situasi baru menjadi kriteria utama yang dicari oleh perusahaan maupun instansi pemerintah. Inilah yang disebut learning agility.
Learning agility bukan sekadar istilah keren di ruang akademik, tetapi panduan keterampilan hidup, di tengah dunia kerja modern yang penuh ketidakpastian. Hanya pegawai yang lincah yang bisa bertahan. Tidak peduli apakah pegawai bekerja di perusahaan, menjadi tenaga pendidik, berkarier sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), atau penegak hukum sekalipun, learning agility adalah modal utama.
Sayangnya, banyak orang masih membayangkan belajar itu duduk di kelas, mendengarkan instruktur, menghafal materi, lalu ujian. Pola ini sudah ketinggalan zaman. Malcolm Knowles melalui konsep andragogy menekankan bahwa pembelajaran orang dewasa harus relevan, berbasis pengalaman, dan berorientasi pemecahan masalah.
Dalam praktiknya, seorang pegawai bisa belajar lebih efektif melalui mempelajari kasus nyata (case learning), problem-based learning, atau diskusi pengalaman dengan rekan kerja. Di dunia ASN, misalnya, pelatihan kepemimpinan menjadi lebih bermakna bila disertai simulasi inovasi yang relevan dengan tuntutan layanan sesuai tugas jabatan dan kewenangannya.
Namun, tantangan masa kini tidak cukup dijawab hanya dengan andragogy. Stewart Hase dan Chris kemudian mengembangkan konsep heutagogy, pendekatan pembelajaran yang menekankan pembelajaran mandiri (self-determined learning). Dengan pendekatan ini, seseorang tidak menunggu pelatihan formal, melainkan aktif mencari sumber belajar: membuka kursus daring, membaca e-book, atau bergabung dengan komunitas digital.
Kombinasi andragogy dan heutagogy inilah yang membentuk learning agility, kemampuan untuk terus belajar ulang (re-learn), meninggalkan kebiasaan lama yang usang, dan menemukan cara baru di tengah ketidakpastian.
Mengapa Learning Agility Penting?

Perubahan datang tanpa permisi. Hari ini kita terbiasa dengan satu sistem, besok sudah muncul aplikasi baru yang wajib dikuasai. Ada empat alasan mengapa learning agility penting, cepat menguasai teknologi baru, berpikir kritis terhadap perubahan, terbuka pada kolaborasi lintas sektor, dan berani bereksperimen.
Contoh sederhana dalam birokrasi, misalnya seorang ASN di bidang kependudukan, dulu hanya mengurus formulir kertas. Kini ia dituntut menguasai sistem daring, mengintegrasikan data, bahkan menjawab pertanyaan publik lewat kanal digital. Tanpa learning agility, ASN akan terkesan gagap dan lamban. Sebaliknya dengan learning agility, ASN bisa beradaptasi cepat, mencari tahu sendiri, dan tetap memberikan layanan terbaik.
Hal serupa juga berlaku di perusahaan swasta. Organisasi dengan karyawan yang lincah belajar akan lebih siap menghadapi disrupsi teknologi, dibandingkan perusahaan yang hanya mengandalkan prosedur lama.
Pertanyaannya, bagaimana melatih learning agility? Pada level individu dimulai dari growth mindset untuk berani gagal, mau mencoba hal baru, dan gemar refleksi diri. Sementara pada level organisasi, dengan menciptakan ekosistem belajar berkelanjutan, misalnya bisa mengembangkan kemampuan melalui Corporate University (Corpu).
Pegawai tidak hanya ikut pelatihan, tetapi juga menjalani action learning project di bidang kerja, bekerja lintas instansi, dan saling berbagi lewat peer coaching.
Menakar Learning Agility

Lingkungan belajar berperan besar dalam melatih learning agility. Setidaknya ada tiga aspek utama yang perlu diperhatikan.
Pertama, fisik dan digital yang menghadirkan ruang kelas interaktif, platform LMS, e-library, hingga innovation hub yang mendorong eksperimen.
Kedua, aspek sosial dengan mendorong adanya budaya yang menganggap kesalahan sebagai bagian dari proses belajar, forum lintas unit, serta program coaching dan mentoring. Terakhir aspek organisasi, yang mengatur tata kelola pembelajaran yang jelas antara peran Dewan Pengarah, Chief Learning Officer (CLO), dan Chief of Group Skill (CGS).
Dalam praktiknya, Corpu bisa membuat program seperti Innovation Lab, atau Leadership Lab, di mana peserta pelatihan membawa masalah nyata dari unit kerja, lalu mencari solusi bersama. Output-nya bukan hanya laporan, melainkan prototipe aplikasi atau rekomendasi kebijakan yang siap diuji.
Contohnya, seorang ASN pasca pelatihan tidak hanya tahu teori pelayanan digital, tapi langsung menginisiasi digitalisasi proses internal. Itulah bukti nyata learning agility.
Pengukuran learning agility tidak bisa dengan ujian hafalan. Ukurannya adalah, apakah pegawai cepat menguasai hal baru, berani mencoba pendekatan berbeda, dan membawa dampak positif bagi tim atau organisasi.
Metode pengukuran yang dapat digunakan, antara lain: self-assessment berbasis kuesioner, 360-degree feedback, simulasi kasus yang menuntut respons cepat, ataupun dengan portofolio pembelajaran, misalnya rekam jejak pembelajaran mandiri di LMS.
Pengukuran terhadap pelatihan yang baik pun tidak bisa hanya sebatas “puas atau tidak puas”. Dengan mengadopsi dan mengadaptasi perspektif dari Model Kirkpatrick, orientasi agility dapat diukur dengan menilai apakah pelatihan menantang peserta untuk berpikir baru? (reaction). apakah peserta mengembangkan pola pikir agile? (learning). apakah peserta berani mencoba hal baru di tempat kerja? (behavior). Dan apakah organisasi menjadi lebih adaptif dan inovatif setelah pelatihan? (results).
Di dunia kerja modern, pegawai yang bertahan bukanlah mereka yang paling pintar, melainkan mereka yang paling lincah belajar. Learning agility menjadi modal utama, baik bagi karyawan swasta, akademisi, maupun ASN.
Organisasi yang merawat budaya belajar berkelanjutan akan lebih adaptif menghadapi perubahan. Individu yang berani meninggalkan cara lama akan lebih sigap menghadapi perubahan. Pada akhirnya, bukan berapa banyak pelatihan formal yang diikuti, tetapi kelincahan mengubah pola pikir dan langkah kerja. Inilah esensi learning agility, panduan survival di era perubahan. (*)