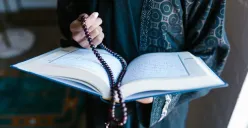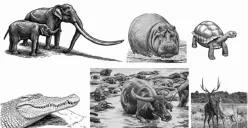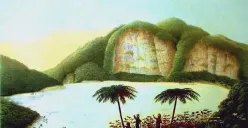BANDUNG dahulu kala kawentar dengan udaranya yang sejuk, bungalow bercorak art deco, dan julukan nan elok: Parijs van Java alias Paris-nya Jawa. Julukan itu bukan cuma sekadar label pemanis bibir, melainkan janji. Ya, janji. Janji ihwal estetika kota, janji ihwal ruang publik yang nyaman, dan janji ihwal ritme hidup yang melambat.
Tapi, kota, seperti juga manusia, tidak diam. Ia terus bergerak. Lihat saja, jalan-jalan yang di masa baheula disesaki pejalan kaki kini disesaki mobil. Trotoar berubah menjadi parkiran dan pusat jual-beli. Bangunan lama tak jarang malah dirobohkan. Beberapa dipoles menjadi kafe atau restoran yang Instagramable. Itu sekadar beberapa contoh betapa kota terus bergerak dan berubah.
Untuk melihat
Bisa dibilang aktivitas turisme di Kota Bandung awalnya cuma terkait dengan aktivitas untuk melihat. Wisatawan datang ke ibukota Jawa Barat ini untuk melihat pemandangan, melihat karya arsitekturnya, maupun melihat kehidupan lokal.
Sekarang? Wisatawan datang untuk membeli. Mereka membeli pengalaman, membeli kopi, membeli foto. Maka, pengalaman pun menjadi komoditas yang bisa dinilai dalam like dan share.
Dan di balik itu semua, ada mesin yang tak terlihat mata kita: geliat kapitalisme kota. Salah satu indikatornya, tanah menjadi komoditas berharga. Developer pun melihat ini sebagai peluang cuan. Lokasi lahan strategis dekat kampus, taman, atau kafe keren langsung menjadi ladang investasi bernilai tinggi.
Bandung yang di masa lampau terikat erat dengan budaya dan melankolia kini harus berhadapan dengan label baru, yakni Paris van Property. Julukan ini mungkin terdengar lucu. Tapi, mengandung ironi. Kota yang dulu dipuja-puji karena pesonanya, kini dipuja-puji karena potensi keuntungan dari tiap meter persegi tanahnya.
Soal selera kopi
Seiring merebaknya, aktivitas turisme membeli pengalaman, fenomena kafe-kafe yang bermunculan di kota ini bukan pula hanya soal selera kopi. Kafe-kafe itu adalah titik pertemuan antara estetika dan pasar. Kafe menjadi semacam etalase, dan etalase itu menarik konsumen yang ingin membeli citra Bandung.
Di saat yang sama, jaringan bisnis kreatif -- desainer, barista, fotografer -- muncul dan tumbuh. Dan itu sehat secara ekonomi. Namun, ketika ruang kreatif bergeser ke logika investasi, kreativitas ikut dipaksa menyesuaikan bahwa estetika harus aman buat feed Instagram, dan bukan lagi tempat eksperimen radikal.
Transformasi semacam ini juga merembet ke kawasan permukiman. Daerah-daerah yang dulu tiisieun sontak berubah menjadi lokasi proyek hunian vertikal. Kos-kosan tradisional berubah menjadi apartemen sewa jangka pendek. Penghuni lama merasakan tekanan, apakah bertahan atau pindah.
Ada yang setuju bahwa segala perubahan yang terjadi di Bandung mendorong infrastruktur yang lebih baik, lebih banyak lapangan kerja, dan lebih banyak peluang bisnis. Tapi, ada pula lho yang menghela nafas, saat keseharian warga lokal semakin terpinggirkan oleh arus kapital nan besar dan tak mengenal nostalgia.
Standar baru

Turisme masa kini tentu saja menuntut standar baru: trotoar harus rapi, taman harus bersih, fasilitas publik perlu terus dipoles. Namun, tuntutan standar itu tak jarang menampilkan kota sebagai panggung semata, bukan sebagai ruang hidup.
Nah, ketika ruang hidup menjadi panggung, maka fungsi sosial kota pun bergeser. Ruang yang dulu untuk interaksi warga berubah menjadi tempat konsumsi. Anak-anak kehilangan lapangan bermain, warung tradisional tergantikan oleh outlet waralaba yang mematok harga di atas rata-rata.
Dalam perspektif ekonomi, hal tersebut sesungguhnya wajar. Bagaimanapun, kota perlu menyesuaikan dirinya pada demand. Sayangnya, politik ruang tak pernah netral. Keputusan zonasi, izin usaha, dan promosi wisata kerap lebih memberi keuntungan pada aktor tertentu -- developer dan investor besar -- ketimbang komunitas lokal.
Dari sisi sosiokultural, perubahan-perubahan yang terjadi tentu saja mempengaruhi identitas kota. Bandung yang dulu identik dengan kesederhanaan dan kehangatan kini ditopang oleh pencitraan urban yang lebih dingin, rapi, terkurasi, dan kadang terasa asing.
Aliran uang
Ekonomi pariwisata sendiri tak selalu menyuburkan pemerataan. Lantaran terkonsentrasi pada pusat-pusat wisata, aliran uang kerap tak sampai menetes rata ke pinggiran. Pengusaha mikro di pasisian mungkin cuma merasakan efek kosmetik -- lebih sedikit --sementara para pelaku besar menuai manfaat utamanya.
Namun, bukan berarti kita harus buru-buru menolak segala perubahan secara brutal dan total. Yang lebih krusial adalah bagaimana mengelola perubahan agar tetap mengucurkan keadilan. Model kolaboratif antara pemerintah, komunitas, dan pelaku usaha kreatif diharapkan bisa menahan arus kapitalisme yang tamak dan rakus.
Salah satu jalan, misalnya, adalah dengan melindungi ruang publik sebagai commons, yakni sumber daya bersama yang dimiliki, diakses, dan dikelola oleh masyarakat untuk kepentingan kolektif, bukan untuk keuntungan pribadi atau korporasi. Menjaga pasar tradisional, memberi insentif untuk bisnis lokal, serta kebijakan zonasi yang melindungi pemukiman dari eksploitasi spekulatif diharapkan pula bisa menjadi semacam tameng atau perisai agar kota tidak sepenuhnya dikuasai pasar.
Praktik perencanaan kota yang inklusif juga diperlukan. Melibatkan warga dalam keputusan pembangunan, transparansi soal izin usaha, dan audit sosial pada proyek-proyek besar adalah praktik yang dibutuhkan.
Akan njomplang
Bila pembangunan hanya dirancang oleh segelintir pihak, hasilnya dipastikan bakal njomplang. Walau demikian, toh kita juga perlu mengapresiasi dinamika ekonomi baru hasil pembangunan yang tercipta di mana banyak orang Bandung mendapat penghidupan dari sektor kreatif. Desainer, barista, content creator, mereka semua mendapat peluang. Tantangannya yaitu memastikan peluang itu bukan bentuk kerja upah murah.
Kelak, Bandung mungkin akan menemukan keseimbangan antara menjadi kota yang dicintai lantaran pesona dan kota yang produktif secara ekonomi. Perjalanan Bandung dari semula Parijs van Java ke Paris van Property sesungguhnya bukan sekadar perkara estetika yang berubah atau bangunan berganti. Ini soal bagaimana kita memilih siapa yang mesti diuntungkan ketika kota terus berevolusi.
Apakah Bandung akan tetap menjadi rumah bagi segenap warganya, ataukah menjadi koleksi properti cantik untuk sekadar dipandangi dari kejauhan, pilihannya ada pada kebijakan, praktik bisnis, dan -- yang paling penting -- pada kepekaan kita terhadap suara-suara kecil yang seringkali tak terdengar. (*)