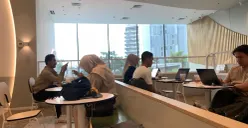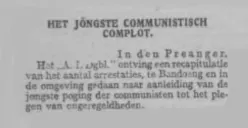Dalam rangka memperingati Hari Buruh, saya terdorong untuk menelusuri asal-usul kata buruh dalam khazanah bahasa dan budaya Sunda.
Sejak kapan istilah ini dikenal oleh masyarakat Sunda, dan bagaimana maknanya berkembang seiring waktu? Apakah sejak awal kata buruh sudah dikaitkan dengan kerja upahan atau gaji berdasarkan waktu tertentu?
Untuk menjawabnya, saya akan menelusuri kamus-kamus Sunda lawas.
Dalam kamus bahasa Sunda pertama, Nederduitsch-Maleisch en Soendasch woordenboek: Benevens twee stukken tot oefening in het Soendasch (1841), susunan Andries de Wilde, saya tidak menemukan adanya lema buruh atau turunannya.
Sebaliknya, dalam kamus tiga bahasa tersebut saya berhasil mendapatkan kata “gadji” dalam bahasa Sunda dan Melayu untuk terjemahan kata “salaris” atau “loon” (Wilde, 1841: 135) dan kata “wedde” atau “jaargeld” (Wilde, 1841: 203) dalam bahasa Belanda. Bahkan kata “jaargeld” diberi arti pula “gadji taoen” atau “wang taoen” (Wilde, 1841: 66).
Temuan ini saya pikir menunjukkan bahwa konsep pembayaran upah secara berkala, khususnya tahunan, telah dikenal dalam bahasa Sunda sejak paruh pertama abad ke-19.
Sebagai catatan, Andries de Wilde kembali ke Belanda setelah menjual perkebunan miliknya di Ujung Berung dan Sukabumi pada 24 Februari 1823. Ia menyerahkan naskah kamusnya kepada Taco Roorda yang menyuntingnya dan memberi pengantar kala menjadi buku pada 13 Maret 1841.
Lebih jauhnya, ini mengandung arti masyarakat Sunda, terutama kalangan terpelajar seperti R.A. Wiranatakusumah III, murid dari de Wilde yang menjabat Bupati Bandung (1794–1829), telah memahami praktik balas jasa atas pekerjaan dalam bentuk uang atau barang.
Namun, lema buruh belum ditemukan dalam kamus de Wilde. Istilah ini baru muncul dalam A Dictionary of the Sunda Language of Java (1862), susunan pemilik perkebunan di Jasinga, Jonathan Rigg.

O ya, sebelum masuk ke istilah buruh, saya menemukan keterangan menarik dari Rigg untuk kata “gaji” yang dibedakannya menjadi dua pengertian.
Pertama, kata tersebut diberi arti “pay, salary, wages; the word is the Dutch Gagie” (membayar, gaji, upah; kata tersebut dari bahasa Belanda Gagie). Kedua, kata gaji diberi arti “fat on animals or man, fat, tallow” (lemak pada hewan dan manusia, lemak) (Rigg, 1862: 118).
Artinya, kedua makna gaji yang kini masih bermakna ganda dalam bahasa Sunda sudah umum diketahui pada pertengahan abad ke-19. Mengingat naskah kamus yang disusun oleh Jonathan Rigg sudah selesai disusun dan diserahkan kepada Perhimpunan Batavia untuk Pengetahuan dan Seni pada tahun 1853, untuk dicetak.
Lalu, bagaimana Jonathan Rigg menggambarkan kata buruh?
Ternyata ia (Rigg, 1862: 73) menyamakan pengertian kata buruh dengan kata gaji, yaitu “wages or recompense given for work done” (upah atau imbalan yang diberikan atas pekerjaan yang telah dilakukan), sementara kata turunannya, “buruhan” diartikan sebagai “pay for work done, wages” (bayaran atas pekerjaan yang dilakukan; upah) dan “Ngala buruhan” sebagai “to take pay for work done; to do work for payment” (menerima bayaran atas pekerjaan yang dilakukan; bekerja untuk mendapatkan upah).
Rigg (1862: 66) juga memuat lema “buburuh” yang diberinya arti “to take wages to do any work; to work for wages” (bekerja untuk memperoleh upah; melakukan pekerjaan dengan menerima bayaran).
Satu lagi, peribahasa “Buburuh nyatu, diupah béas” yang berarti “taking pay for eating, he is still rewarded with rice: a Sunda proverb, for doing everything to the best advantage” (menerima bayaran untuk makan, tetapi tetap mendapat imbalan berupa beras: peribahasa Sunda yang menggambarkan seseorang yang selalu mampu mengambil keuntungan terbaik dari setiap situasi).
Peribahasa tersebut saya pikir lahir dari adanya kesadaran budaya atas praktik kerja upahan dan sekaligus kecerdikan sosial dalam konteks relasi kerja yang dilatari oleh budaya kerja upahan dalam budaya Sunda. Sekaligus menunjukkan bahwa hingga pertengahan abad ke-19, upah atau gaji kerja berupa beras rupanya sudah umum diberikan.
Baca Juga: Munaip Saleh, Raja Balap Sepeda Raksasa Pertama Tour de Java
Dari penelusuran saya di atas, terlihat bahwa masyarakat Sunda sejak lama mengenal konsep kerja upahan atau kerja yang diupah, baik dalam praktik maupun dalam ungkapan bahasanya.
Dalam hal tersebut, istilah buruh, meskipun relatif lebih baru masuk dalam kamus dibanding istilah gaji, mencerminkan berkembangnya relasi kerja di tengah perubahan ekonomi dan sosial pada abad ke-19 sebagai dampak dari praktik Sistem Priangan (1720-1830) dan Sistem Tanam Paksa (1830-1870).
Dalam kerangka peringatan Hari Buruh, penelusuran kamus ini memperlihatkan bahwa kerja dan upah bukan hubungan ekonomi semata, melainkan bagian dari konstruksi budaya yang hidup dan terawetkan dalam bahasa serta peribahasa masyarakat Sunda. (*)