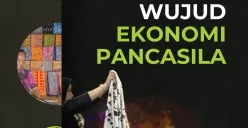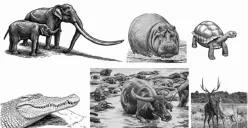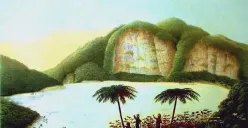Reputasi di dunia digital kini tidak hanya dibangun melalui konsistensi dan integritas, tetapi juga dapat dipelihara, diperjualbelikan, bahkan ditebus dengan angka yang mencengangkan.
Jika di masa lalu citra baik adalah buah dari rekam jejak dan kredibilitas, kini reputasi bisa dipoles melalui strategi yang membingungkan akal sehat dan kadang melanggar hukum.
Kisah Nikita Mirzani menjadi salah satu contoh mencolok. Ia didakwa memeras Reza Gladys, seorang dokter kecantikan, sebesar empat miliar rupiah agar produk skincare milik Reza tetap ditampilkan positif di media sosial. Motifnya tampak sederhana: menjaga popularitas.
Di tengah derasnya arus opini digital, satu narasi negatif bisa meruntuhkan kepercayaan publik dalam hitungan jam. Maka, mempertahankan citra bukan lagi tentang pembuktian kualitas, melainkan tentang kontrol narasi dengan segala cara.
Sosok lain yang menjadi sorotan adalah food vlogger misterius, Codeblu. Ia dituding meminta bayaran antara tiga ratus lima puluh hingga enam ratus juta rupiah kepada para pemilik usaha kuliner agar ulasan negatif dihapus atau diganti dengan konten positif.
Tarif resminya bahkan mencapai lima ribu dolar Amerika untuk satu video TikTok. Ia juga sempat menuding toko roti ternama menyumbangkan kue basi ke panti asuhan. Setelah toko tersebut membantah dan memberikan klarifikasi, muncul dugaan bahwa Codeblu meminta uang agar video itu dihapus.
Meski dibantah sebagai pemerasan dan disebut sebagai tarif jasa, publik melihat ini sebagai praktik manipulatif yang mengandalkan pengaruh digital untuk menekan, bukan untuk memberi edukasi.
Belum selesai riuhnya kasus tersebut, kesaksian mengejutkan datang dari Samira atau Doktif, dokter kecantikan sekaligus kreator konten. Dalam sidang kasus Nikita, ia mengungkap bahwa dirinya sempat diminta oleh suami Reza Gladys untuk memberikan ulasan positif. Karena merasa terus dikejar dan didesak, Doktif menyebut angka dua puluh miliar rupiah secara spontan.
Maksudnya hanya untuk mengetes, namun mengejutkannya, dua hari kemudian cek senilai dua puluh miliar itu benar-benar diberikan. Menurut pengakuannya, ia tidak pernah memberikan ancaman atau meminta uang sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa dorongan untuk membeli citra di era digital bisa begitu besar dan tidak rasional.
Fenomena ini bukan hal baru. Pada tahun 2015, publik pernah dikejutkan oleh kasus tiga pengelola akun Twitter @triomacan2000, yakni Edy Syahputra, Raden Nuh, dan Harry Koes Harjono. Mereka terbukti memeras Direktur Utama PT Tower Bersama Group dan pejabat PT Telkom dengan modus mencemarkan nama melalui unggahan media sosial.
Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis empat hingga lima tahun penjara. Meski hukum telah bicara, praktik serupa justru terus bermunculan dalam format yang lebih tersembunyi dan kompleks.
Komoditas Citra

Keempat kasus ini menggambarkan pola yang mencemaskan. Citra menjadi komoditas yang bisa dinegosiasikan. Upaya mempertahankan nama baik di dunia maya telah melahirkan praktik-praktik ekstrem, mulai dari manipulasi narasi hingga pemerasan terselubung.
Di tengah tekanan untuk selalu tampil sempurna, para aktor digital cenderung rela mengorbankan etika dan kebenaran.
Secara akademik, fenomena ini dapat dijelaskan melalui pemikiran Goffman dalam karya klasiknya The Presentation of Self in Everyday Life (1959). Ia menyatakan bahwa manusia senantiasa menampilkan diri dengan berbagai peran di hadapan audiens sosial.
Di era digital, panggung itu semakin luas dan terang, serta tidak lagi mengenal waktu jeda. Kegagalan memainkan peran bisa berujung pada keruntuhan identitas secara sosial dan ekonomi.
Pemikiran Goffman dilengkapi Jia Tolentino dalam Trick Mirror (2019), yang mengkritik bagaimana budaya internet menciptakan dorongan narsistik kolektif.
Ia menyebut masyarakat modern membangun versi ideal dari dirinya di ruang digital bukan untuk tumbuh, tetapi demi memenuhi ekspektasi popularitas. Diri yang autentik tergantikan oleh diri yang dikonstruksi demi validasi.
Penelitian Onifade (2021) menunjukkan bahwa ketergantungan pada validasi sosial melalui media digital membentuk harga diri yang rapuh. Ketika eksistensi bergantung pada jumlah pengikut, likes, dan komentar, maka seseorang akan terdorong melakukan apa pun demi mempertahankan performa digitalnya.
Hal ini diperkuat studi Lin et al. dalam jurnal MDPI (2025) yang mengamati praktik presentasi diri palsu sebagai strategi bertahan dalam lanskap persaingan popularitas. Ini bukan sekadar komunikasi, tapi pergelutan psikologis dan pertarungan moralitas.
Pada akhirnya, ketika seseorang meminta dua puluh miliar demi ulasan positif, atau influencer menetapkan tarif lima ribu dolar untuk satu konten, kita sedang menyaksikan pergeseran nilai.
Reputasi tidak lagi dibangun di atas landasan integritas, tetapi dikelola sebagai aset yang bisa ditukar. Etika publik tergantikan oleh logika untung rugi. Dan komunikasi kehilangan makna dasarnya: menyampaikan kebenaran.
Artikel ini tidak bertujuan menghakimi siapa pun --apalagi penulis bukan aparat hukum. Sebatas mengajak kita berpikir ulang.
Di tengah budaya layar yang mendikte nilai manusia, di mana nama baik bisa ditebus dengan uang dan tekanan, kita perlu mempertanyakan: Apakah dunia digital ini masih berlandaskan komunikasi yang sehat atau telah berubah menjadi pasar nilai yang banal dan transaksional? (*)