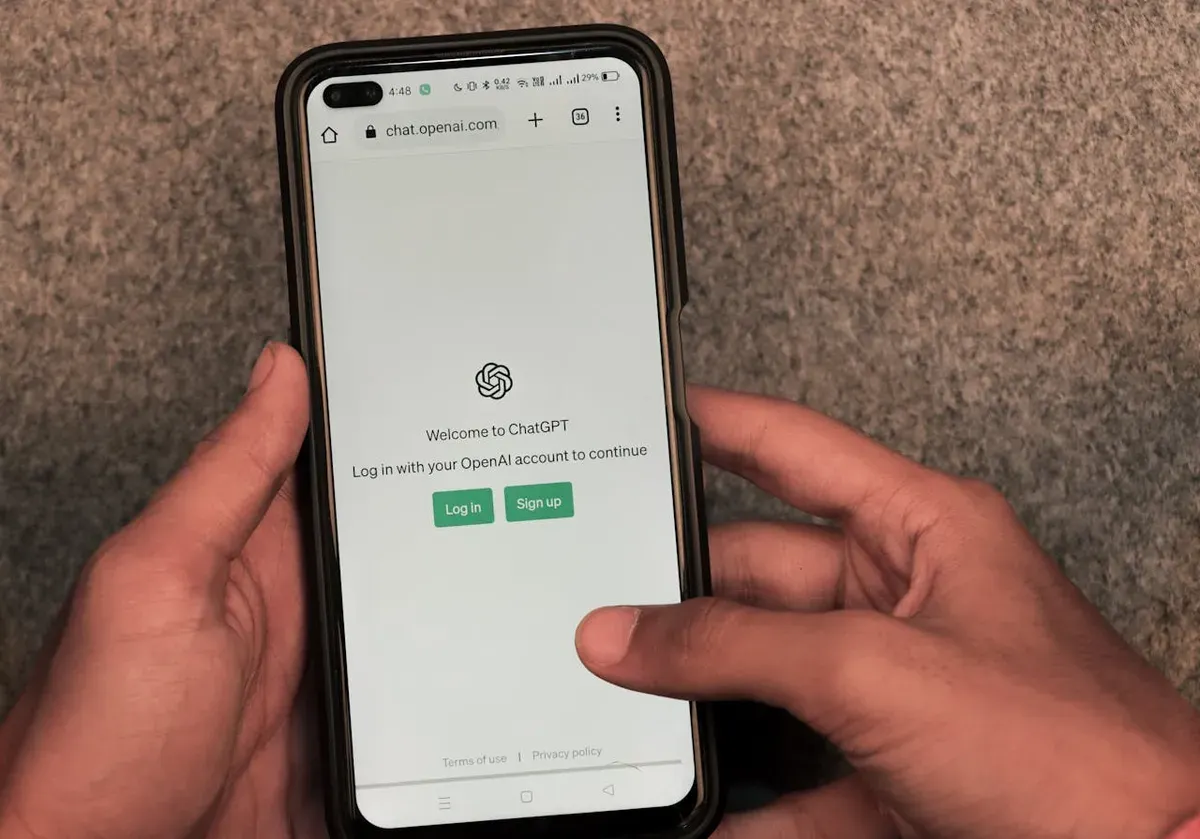Di sela perkuliahan, seorang mahasiswa bercerita tentang kebiasaan barunya “curhat” dengan salah satu aplikasi AI (Artificial Intellegence).
Ia bilang, setiap kali merasa stres atau kewalahan saat menghadapi tekanan hidup, AI lebih nyaman untuk dijadikan teman, alasannya sederhana, AI tidak pernah menghakimi, selalu siap mendengarkan, dan yang paling penting AI lebih solutif dari pada teman-teman di kelasnya.
Pengakuan ini tentu memunculkan beragam reaksi dari benak saya, antara terkejut, ingin memahami lebih jauh dan bertanya-tanya tentang makna dibalik kebiasaan barunya. Apakah ini cerminan dari kebutuhan emosional yang tak terpenuhi, atau justru indikasi pergeseran dalam membangun relasi dan mengekspresikan diri di kalangan generasi muda?
Mahasiswa tersebut merupakan salah satu dari ribuan kasus atas fenomena yang sedang terjadi. Warga digital kini semakin akrab dengan kehadiran AI.
Misalnya ChatGPT, Replika, dan Woebot, mereka hadir sebagai teman digital dengan aksesibilitas 24 jam. AI juga memberikan respons yang cepat dan netral secara emosional, karakteristik yang menjadi daya tarik utama bagi kalangan muda.
Menurut penelitian yang dilakukan oleh Morris et al. (2022) dalam Computers in Human Behavior, netralitas emosional AI membantu mengurangi kecemasan sosial pada pengguna yang takut mendapat penilaian negatif dari orang lain. Artinya, AI memberikan ruang aman bagi anak muda untuk mengekspresikan diri tanpa rasa takut dihakimi.
Survey yang dilakukan kepada generasi muda di Australia menyatakan bahwa, dalam mencari dukungan emosional, mereka lebih sering menggunakan chatbot AI dan menghindari bantuan professional karena stigma dan keterbatasan akses (Medibank & The Growth Distillery, 2024).
Begitupun dengan Denmark, sekitar 2,4% siswa sekolah menengah menggunakan chatbot untuk dukungan sosial, meski interaksi manusia tetap dibutuhkan (Psypost.org, 2024).
Sementara itu, di Taiwan dan China, AI menjadi alternatif murah dan mudah diakses untuk mengatasi tekanan psikologis generasi muda (The Guardian, 2025).
Di Indonesia, meskipun belum ada data resmi, tren global ini kemungkinan besar tercermin juga di kalangan anak muda yang aktif menggunakan teknologi.
Fenomena tersebut selaras dengan teori Media Richness dari Draft dan Lengel (1986), dijelaskan bahwa media komunikasi yang kaya mampu memenuhi kebutuhan komunikasi interpersonal yang efektif. AI, dengan segala “kekayaannya” mampu merespon cepat dan menyesuaikan kebutuhan pengguna.
Selain itu, teori Parasocial Interaction (Horton & Wohl, 1956) juga relevan, bagaimana seseorang bisa membangun komunikasi satu arah dengan media (dalam hal ini AI), yang membuat pengguna merasa didengar dan dihargai meski interaksinya tidak bersifat timbal balik seperti pada hubungan manusia.
Lalu, dengan semua fakta dan teori tersebut, lahir pertanyaan menggelitik, Apakah AI benar-benar bisa menggantikan manusia sebagai teman curhat?
Pertanyaan ini melahirkan jawaban yang rumit, di satu sisi kelahiran AI memang memenuhi kebutuhan emosional tertentu (kebutuhan untuk didengar, diterima dan dimengerti), namun di sisi lain, ada dimensi relasional dan emosional yang tidak bisa digantikan sepenuhnya oleh entitas digital.
Dari perspektif psikologis, AI membantu pengguna memproses pikiran lebih runut, memvalidasi perasaan dengan sistematis, bahkan terkadang memberi saran dan solusi dengan logis. Seperti yang dikatakan mahasiswa saya, bahwa AI lebih “solutif” dibandingkan dengan teman sekelasnya.
Namun, perlu diingat bahwa solusi yang diberikan AI bukan hasil dari empati sejati, melainkan dari model statistik berbasis data. Artinya, kehadiran AI bukan berdasarkan rasa peduli, melainkan karena program yang dirancang untuk merespon sesuai permintaan. Sangat ironis, pengguna merasa dimengerti “sesuatu” yang sebenarnya tidak pernah benar-benar mengerti.
Tren curhat digital ini menunjukan kecenderungan baru yang menarik, beberapa peneliti menyebut gejala ini sebagai emotional outsourcing, yaitu kecenderungan untuk melakukan proses mengelola emosi kepada pihak luar, seperti aplikasi meditasi, chatbot AI, atau video self-helf di media sosial.
Baca Juga: Ketentuan Kirim Artikel ke Ayobandung.id, Total Hadiah Rp1,5 Juta per Bulan

Tidak bisa dimungkiri, AI memberi ruang baru dalam cara kita mencari dukungan emosional. AI menjadi “penolong” bagi mereka yang merasa tidak punya ruang aman di dunia nyata. Bahkan dalam beberapa kasus, AI justru membantu seseorang mengenali bahwa dirinya sedang tidak baik-baik saja, lalu mendorongnya untuk mencari pertolongan professional.
Pada dasarnya Ini bukan hal buruk, tapi jika dilakukan terus-menerus tanpa diimbangi refleksi diri atau interaksi nyata dengan manusia, perlahan-lahan seseorang akan kehilangan kepekaan emosionalnya, baik terhadap dirinya sendiri ataupun terhadap orang lain.
Saya tidak mengharamkan AI, atau melarang generasi muda untuk menggunakannya. AI bisa sangat membantu dalam situasi tertentu, ia bisa menjadi ruang awal untuk menata pikiran, menenangkat hati, atau sekadar menjadi teman “bicara” tanpa rasa takut dinilai. Tapi penting untuk diingat, AI bukan sahabat sejati yang sebenarnya. Ia bisa merespon, tapi tidak bisa benar-benar mengerti. Ia bisa menenangkan, tapi tidak bisa memberi pelukan.
Karena itu, literasi emosional perlu berjalan seiring dengan literasi digital. Anak muda harus lebih mengenali dan memahami emosinya sendiri, bukan hanya lewat layar, tapi juga lewat percakapan langsung, relasi hangat, dan pengalaman nyata.
Di sinilah peran orang tua menjadi sangat krusial, tugasnya bukan menjadi polisi moral atau penjaga pagar teknologi, melainkan menjadi pendengar setia, yang hadir, yang tidak buru-buru menyela, yang tidak langsung menyalahkan. Anak muda tidak selalu butuh nasihat, kadang mereka hanya ingin tahu bahwa ada seseorang yang mau mendengarkannya dengan sungguh-sungguh.
Mungkin apa yang dilakukan mahasiswa saya bukan hanya tentang “lebih memilih AI”, bisa jadi merupakan bentuk adaptasi terhadap dunia yang semakin sunyi dalam keramaian. Kita hidup di tengah banyak koneksi, tapi jarang merasa benar-benat terhubung. Percakapan makin cepat, tapi esensinya makin dangkal.
Inilah saatnya kita bertanya ulang, apakah AI benar-benar hadir untuk kita, atau hanya sekedar pantulan dari diri sendiri yang semakin jarang di dengar? Apakah kenyamanan curhat dengan AI merupakan solusi, atau hanya pelarian sesaat dari kebutuhan kita yang lebih dalam, seperti ingin dimengerti, diterima dan memiliki hubungan yang dekat dengan orang lain? Pertanyaan ini bukan untuk dijawab cepat-cepat, bukan soal benar atau salah, tapi untuk dipikirkan dan direnungkan.
Baca Juga: Ketentuan Kirim Artikel ke Ayobandung.id, Total Hadiah Rp1,5 Juta per Bulan
Teknologi memang membuat banyak hal jadi lebih mudah. Tapi tak semua yang mudah membuat kita lebih kuat. Kadang, justru lewat hubungan yang tidak sempurna, membingungkan, melelahkan, bahkan menyakitkan, membuat kita belajar menjadi manusia yang utuh.
Tren “curhat digital” tidak salah, tapi saya percaya, kita semua tetap butuh seseorang yang hadir bukan karena diprogram, melainkan karena rasa kepedulian. Tugas kita hari ini bukan hanya soal bagaimana menggunakan AI dengan bijak, tapi juga bagaimana kembali membangun ruang-ruang kepercayaan antar manusia. (*)