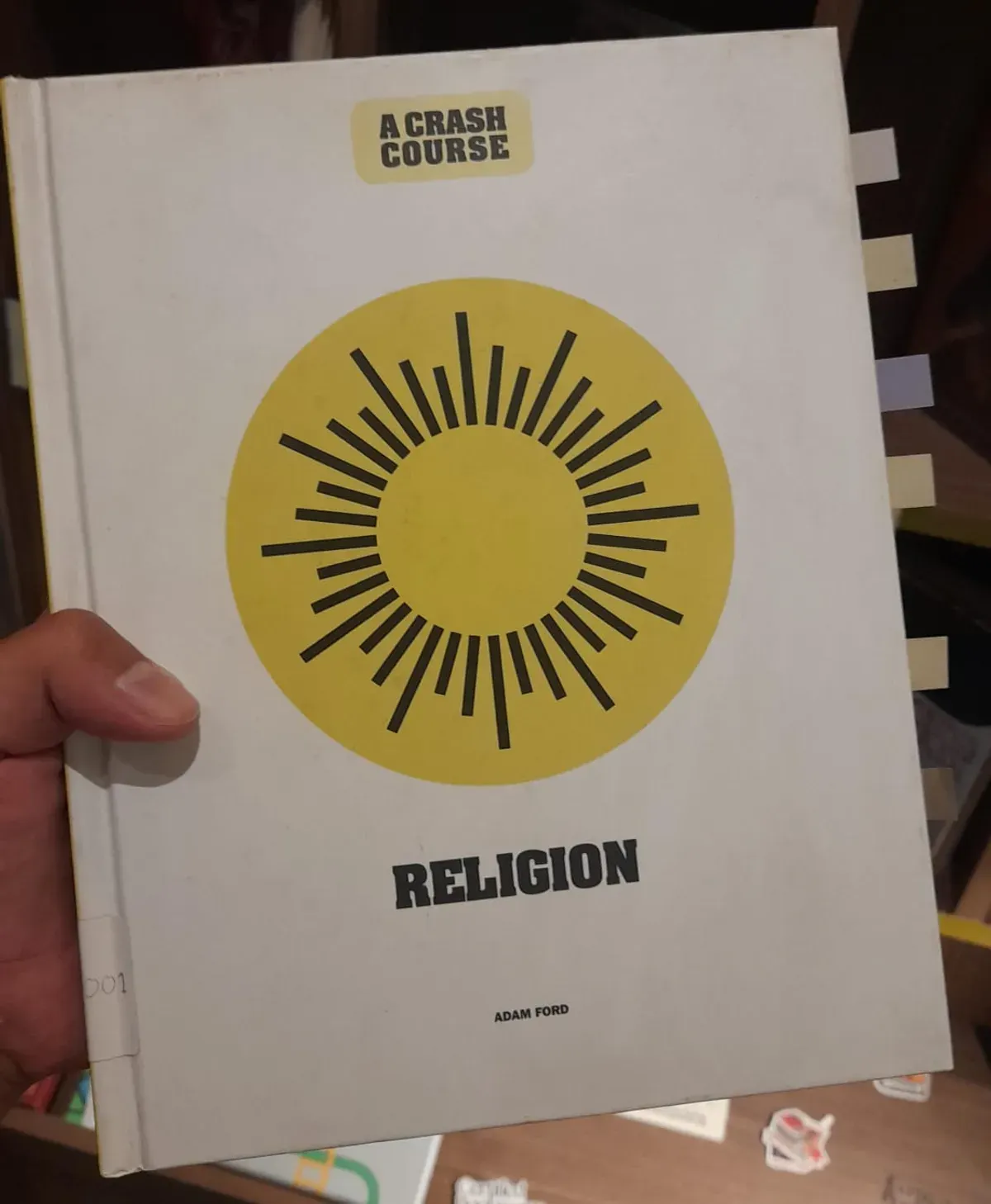Kalau dengar kata “agama” yang kebayang di kepala kebanyakan orang sudah semacam template default yang tidak pernah diubah dari zaman SD. Agama itu harus ada Tuhan, harus punya kitab suci, ada pendiri atau nabi, ada tempat ibadah, ada hari raya, dan pastinya ada umatnya. Seolah-olah kalau tidak punya salah satu dari itu, langsung dianggap bukan agama.
Masalahnya, cara pandang itu sering banget dipakai buat bikin dunia agama terlihat rapi dan gampang dipahami. Katanya biar enggak bingung, biar gampang diajarin, eh ujung-ujungnya biar rukun juga. Tapi justru di situ letak masalahnya. Karena begitu kita malah maksa menyeragamkan semua agama, yang akhirnya kita kehilangan sisi paling hidup dari agama itu sendiri. Ialah keunikan, identitas, keragaman, dan kedalaman maknanya.
Padahal kalau saja kita mau beranjak sedikit, membongkar kejumudan pikiran, kita bisa terperangah. Ternyata dunia agama itu jauh lebih mempesona dan tidak bisa dipaksa pakai standar tertentu. Coba bayangkan ada agama tidak dikenali tanpa nama, ada yang tidak punya pendiri, bahkan ada yang tidak punya Tuhan. Dan semuanya betulan hadir, hidup di dunia kita, dipraktikkan, dan membentuk sistem religi bagi jutaan orang sampai sekarang.
Mencicip Keberagaman
Misalnya Buddha dan Jain. Dua-duanya tidak percaya sama konsep Tuhan personal. Aneh kan? Tapi mereka tetap layak disebut agama. Yang mereka kejar bukan sosok Sang Pencipta, tapi solusi supaya kita bisa keluar dari penderitaan. Fokusnya bukan menyembah, tapi melatih diri sendiri. Kalau kita bandingkan sama konsep agama mainstream yang penuh doa dan pengharapan pada Tuhan, agama ini kayak kebalikannya. Namun justru di situ menariknya, bahwa agama tidak melulu vertikal, bisa menekankan potensi diri.
Terus lihat Hindu, kasusnya juga “nyentrik”. Biasanya kita pikir bahwa setiap agama itu dimulai dari titik satu orang hebat, lalu pecah jadi macam-macam aliran. Tapi Hindu awalnya justru keragaman aliran, variasi bentuk pemujaan, sebuah klaster religi, baru lama-lama dianggap satu agama. Kayak band indie yang banyak gaya, terus orang-orang di luar sana menyebutnya “Oh ini ternyata satu genre”. Agama Hindu jadi bukti, agama yang sama tidak harus seragam.
Ada pun Konghucu. Banyak yang mengira bahwa Konfusianisme itu bukan agama, katanya cuma filsafat. Memang karakter agama ini khas banget. Dia tidak tertarik buat bahas panjang lebar soal surga dan neraka, ajarannya lebih berfokus pada cara kita jadi manusia yang beneran manusiawi. Punya rasa malu, hormat, sopan, tanggung jawab, dan peran sosial. Agama ini menekankan moral dan pendidikan. Kita tidak disuruh meninggalkan dunia, tapi justru diajarkan caranya bikin dunia ini lebih beres.
Di sisi lain, ada Sikh. Agama ini tentunya tidak kalah uniknya. Dalam pandangan Sikh, yang jadi “nabi” itu justru kitabnya sendiri, Guru Granth Sahib. Kitabnya dianggap hidup, bukan sebatas teks mati. Ia dibacakan, dijaga, diperlakukan kayak manusia suci. Jadi penerus pemungkas Guru Nanak, Sang Pendiri.
Kini kita beralih pada Baha’í, agama yang berhasrat menyatukan semua manusia di dunia. Dia tidak punya rumah ibadah khusus dan tidak memiliki aliran. Prinsipnya simple bahwa semua agama dipandang sebagai satu rantai panjang menuju kebenaran. Setiap nabi kayak episode dalam satu seri besar yang belum kelar. Kita bayangkan saja kayak multiverse tapi versi relius. Baha’i adalah agama yang tidak memiliki pemuka agama tunggal, kepemimpinan dijalankan secara kolektif.
Yahudi, ini lebih rumit lagi, karena dia merupakan agama sekaligus identitas kebangsaan. Penganutnya tidak hanya percaya dan melakukan ritual bersama, tapi juga “terlahir” dari sumber yang sama. Kayak agama dan etnisitas yang bersatu. Spiritualitasnya tidak bisa dipisah dari sejarah dan politik. Hidup sebagai bangsa Yahudi sudah bagian dari religiusitas. Yahudi adalah agama lokal yang mengglobal.

Sementara Shinto malah tampak lebih santai. Banyak orang Jepang sendiri bilang kalau mereka tidak beragama, tapi “lucunya” masih rajin datang ke kuil dan mengucap terima kasih ke Kami. Mereka bisa buddhis sekaligus shinto-an, meski kadang di data ditulis sebagai ateis juga. Hal ini jadi bukti kalau agama tidak harus jadi label dan identitas. Kadang, yang paling religius itu justru yang tidak merasa beragama.
Agama Tao, itu sudah level lain. Tao dipahami sebagai jalan, prinsip, kebenaran, struktur dasar dari realitas semesta, tapi sekaligus juga bukan semuanya itu. Agama ini mengajarkan bahwa yang tidak bisa dijelaskan justru yang paling hakiki. Inilah pusat beragamanya. Tao ibarat udara. Kita tidak lihat, tapi kita hirup tiap hari.
Lanjut ke Zoroaster, agama tua dari Persia, yang memberi ide tentang pertarungan abadi antara terang dan gelap. Konsep setan yang kita kenal sekarang pada asalnya dari sini. Dalam agamanya, dunia dilihat seperti arena tarik-menarik dua energi kosmik, dan manusia disuruh pilih mau di sisi mana. Unik lagi ya kan? Zoroaster menunjukkan bahwa agama itu tidak harus monoteistik atau politeistik, ia bisa berpijak pada keyakinan pada dua kekuatan Maha Dahsyat.
Begitu juga Islam. Banyak yang pikir Islam itu kaku karena fokusnya ke hukum dan politik. Padahal hal tersebut cuma salah satu sisinya. Di dalamnya, agama ini bicara tentang keseimbangan, iman diterjemahkan jadi tindakan sosial, jadi keadilan. Kalau kita lihat dari situ, Islam justru salah satu agama yang praktis di dunia. Bukan cuma soal akhirat, tapi tentang hidup yang sekarang juga. Makanan halal dan bank syariah berakar dari pemahaman ini.
Lalu ada Kristen. Banyak yang kira gereja itu bangunannya, padahal inti Kekristenan justru persekutuannya. Bagi agama ini religiusitas tidak bisa diekspresikan sendirian, seorang kristiani mesti hidup dalam komunitas. Demikianlah makna sejati dari gereja, dari identitas sejatinya orang-orang Kristen. Agama selalu menuntut kebersamaan.
Catatan Penutup
Jadi, begitulah sedikit fun fact tentang dunia agama-agama. Mereka semua hidup dengan caranya sendiri. Ada yang mistis, ada yang etis, ada yang kolektif, ada yang personal banget. Masing-masing tumbuh dari konteksnya sendiri, dengan logika dan keindahan yang tidak bisa diseragamkan.
Buat besok-besok yang masih bilang “semua agama kan intinya sama”, boleh dong kita pikir ulang. Jangan lagi tergesa-gesa ya, apalagi sampai salah kaprah. Memukul rata atas nama kerukunan malah bikin kita kehilangan kesempatan buat benar-benar mengenal setiap agama. Kalau semua dianggap sama, ya kapan kita belajar menghargai bedanya? Justru dengan berani melihat keunikan tiap agama, kita bisa merayakan keberagaman dengan cara yang lebih jujur dan mendalam. (*)