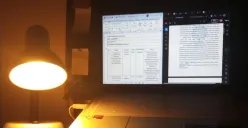Fenomena begadang, seolah-olah menjadi kebiasaan umum bagi kalangan mahasiswa. Ketika jam menunjukkan pukul dua dini hari, banyak mahasiswa justru baru memasuki fase kedua dari aktivitas hariannya, ada yang menyelesaikan tugas kuliah, berdiskusi lewat Zoom, memperbaiki laporan praktikum, atau hanya sekadar menatap layar sambil menyeruput kopi yang sudah tidak panas.
Kebiasaan ini seolah menjadi identitas tidak resmi dalam dunia kampus, seakan-akan mahasiswa sejati adalah mereka yang akrab dengan malam panjang. Pertanyaannya, bagaimana kebiasaan ini bisa begitu melekat, dan apakah benar begadang membuat mereka lebih produktif?
Sebagian besar mahasiswa meyakini bahwa malam hari adalah waktu paling tepat untuk fokus. Sunyi, minim gangguan, dan memberikan perasaan seolah dunia hanya milik mereka. Dari sisi sains, pernyataan ini memiliki hubungan dengan ritme sirkadian, yaitu jam biologis tubuh yang mengatur kapan seseorang merasa segar atau mengantuk. Namun ritme ini sangat fleksibel dan bisa dipengaruhi oleh kebiasaan seseorang.
Penelitian dari National Sleep Foundation menjelaskan bahwa jadwal tidur yang sering bergeser akan mengacaukan produksi hormon melatonin, hormon yang memicu rasa kantuk. Semakin sering seseorang begadang, semakin lambat melatonin dilepas dan tubuh akan mulai produktif justru pada jam-jam ketika seharusnya istirahat.
Dengan kata lain, mahasiswa bukan terlahir sebagai makhluk nokturnal, kebiasaan tersebut terbentuk oleh kebiasaan yang terus diulang. Survei di beberapa kampus besar di Indonesia juga menunjukkan pola serupa dimana mayoritas mahasiswa tidur di rentang tengah malam hingga pukul dua pagi, dan hal ini lebih dianggap sebagai budaya daripada pilihan sadar.
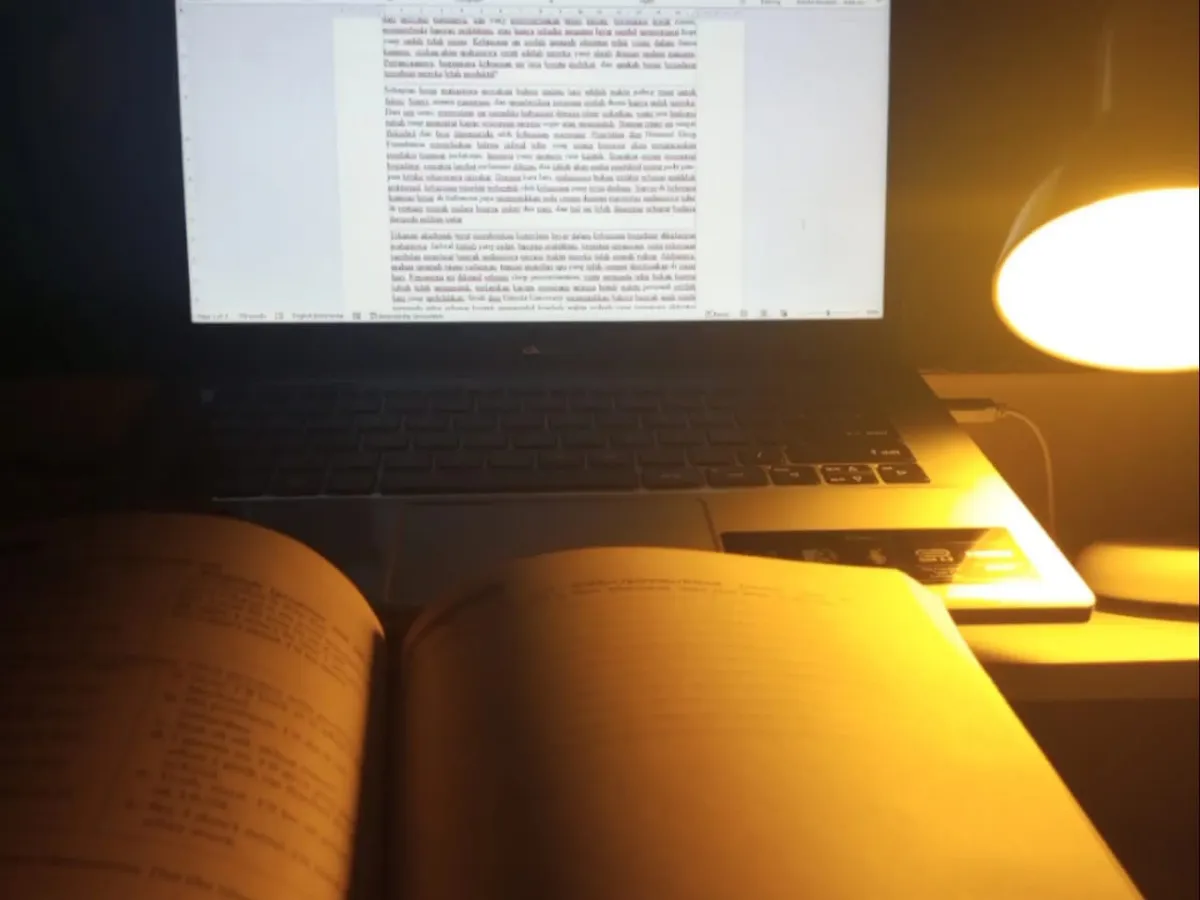
Tekanan akademik turut memberikan kontribusi besar dalam kebiasaan begadang dikalangan mahasiswa. Jadwal kuliah yang padat, laporan praktikum, kegiatan organisasi, serta pekerjaan sambilan membuat banyak mahasiswa merasa waktu mereka tidak pernah cukup. Akibatnya, malam menjadi ruang cadangan, tempat menebus apa yang tidak sempat diselesaikan di siang hari.
Fenomena ini dikenal sebagai sleep procrastination, yaitu menunda tidur bukan karena tubuh tidak mengantuk, melainkan karena seseorang merasa butuh waktu personal setelah hari yang melelahkan. Studi dari Utrecht University menunjukkan bahwa banyak anak muda menunda tidur sebagai bentuk mengambil kembali waktu pribadi yang terpotong aktivitas lain. Dalam suasana tenang itulah muncul ilusi produktivitas dimana mahasiswa merasa bekerja lebih baik pada malam hari, padahal penelitian dari Harvard Medical School menemukan bahwa kurang tidur dapat menurunkan efisiensi belajar hingga 40 persen.
Begadang bukan hanya tentang rasa kantuk esok hari, karena tubuh dan otak bekerja lebih keras dari yang terlihat oleh fisik. Bagian otak bernama prefrontal cortex yang bertanggung jawab pada fokus dan pengambilan keputusan akan menurun kinerjanya ketika tidur tidak cukup. Centers for Disease Control and Prevention bahkan menyebutkan bahwa kurang tidur selama 17 jam setara dengan kemampuan fokus seseorang yang memiliki kadar alkohol ringan dalam darah. Selain itu fenomena begadang juga menyebabkan emosi juga ikut terdampak.
Penelitian dari University of California menunjukkan bahwa kurang tidur meningkatkan aktivitas amigdala hingga 60 persen, membuat seseorang lebih mudah tersinggung, sedih, atau stres. Pada saat bersamaan, proses konsolidasi memori dengan mekanisme otak menyimpan informasi baru akan terhambat. Akibatnya belajar sambil begadang membuat materi sulit menempel meski waktu belajar terasa lebih lama. Jika hal ini terjadi terus menerus, dampaknya dapat meluas ke kesehatan fisik. American College Health Association mencatat bahwa sekitar 35–40 persen mahasiswa mengalami kurang tidur kronis yang memengaruhi imunitas, metabolisme, dan fungsi tubuh lainnya.

Jika semua efeknya sudah cukup jelas, mengapa kebiasaan ini tetap dipertahankan? Jawabannya berkaitan dengan psikologi dan budaya. Begadang memberikan mahasiswa perasaan sedang memegang kendali penuh atas waktunya terutama setelah hari yang penuh tuntutan.
Selain itu, ada unsur kebersamaan. Ketika satu kos, satu kelas, atau satu kelompok tugas sama-sama begadang, terbentuk solidaritas yang membuat kebiasaan itu terasa wajar. Budaya kampus juga memperkuatnya. Skripsi identik dengan begadang. Laporan praktikum identik dengan begadang. Kerja kelompok sering kali baru bisa dilakukan larut malam. Lama kelamaan muncul narasi tidak resmi bahwa mahasiswa yang tidur cepat dianggap kurang berjuang. Padahal narasi tersebut lebih merupakan mitos sosial daripada kebutuhan biologis.
Baca Juga: Bisakah Transportasi Publik Memutus Rantai Kemacetan?
Meski begitu, produktivitas tidak mesti dibayar dengan jam tidur yang dikurangi. Berbagai riset justru menunjukkan bahwa tidur cukup adalah faktor penting yang meningkatkan kemampuan berpikir, fokus, dan daya tahan terhadap stres. Stanford University menyebutkan bahwa mahasiswa yang tidur 7–8 jam per hari memiliki performa akademik lebih baik daripada mereka yang menambah jam belajar dengan mengorbankan tidur.
Strategi sederhana seperti menjaga konsistensi jam tidur, membatasi kafein di sore hari, memisahkan waktu belajar dari waktu bermedia sosial, hingga menggunakan teknik Pomodoro dapat membantu mengurangi kebutuhan lembur tanpa menurunkan produktivitas.

Begadang memang tidak selalu bisa dihindari, terutama saat masa intens seperti menjelang ujian atau menyelesaikan skripsi. Namun menjadikannya gaya hidup adalah pilihan yang kurang baik. Tubuh lebih cepat lelah, emosi lebih sulit dikendalikan dan kemampuan belajar justru menurun.
Banyak mahasiswa bangga karena mampu bertahan hingga pagi, tetapi sains memberikan pesan yang berbeda. Istirahat adalah bagian dari kecerdasan, bukan kebalikannya. Kuliah tidak ditujukan untuk melihat siapa yang paling lama tidak tidur, melainkan siapa yang paling mampu mengelola energi, waktu, dan kesehatan diri. (*)