AYOBANDUNG.ID – Selain isu greenwashing yang menarik untuk dikuliti, soal adaptasi perubahan iklim pun menjadi topik hangat yang dibahas dalam Business and Climate Media Initiative Virtual Workshop yang diinisiasi oleh Earth Journalism Network (EJN).
Pakar lingkungan asal Bangladesh, Ahsan Uddin Ahmed, menegaskan bahwa adaptasi merupakan kunci penting agar masyarakat mampu bertahan menghadapi dampak perubahan iklim yang kian nyata dan tak bisa dicegah.
Ahmed memaparkan hasil telaahnya tentang distribusi pendanaan iklim global yang masih timpang, di mana sebagian besar mengalir ke proyek mitigasi.
Dalam konteks perubahan iklim, mitigasi dan adaptasi memiliki fokus yang berbeda.
Mitigasi merujuk pada upaya untuk menghindari dan mengurangi emisi gas rumah kaca ke atmosfer. Tujuannya adalah untuk mengatasi akar penyebab perubahan iklim dengan mengurangi jumlah gas yang memerangkap panas. Contoh tindakan mitigasi termasuk beralih ke sumber energi terbarukan, meningkatkan efisiensi energi, dan mengurangi deforestasi.
Sedangkan adaptasi adalah upaya untuk mempersiapkan dan menyesuaikan diri terhadap dampak perubahan iklim yang sudah terjadi atau yang akan datang. Tujuannya adalah untuk mengurangi kerentanan terhadap dampak-dampak tersebut. Contoh tindakan adaptasi seperti menghemat air, mengelola sampah, menanam pohon, serta menggunakan transportasi ramah lingkungan. Upaya ini bisa diperkuat dengan membangun rumah yang lebih hemat energi, menjaga kesiapsiagaan bencana, dan menumbuhkan kesadaran bersama sejak dini.
Singkatnya, mitigasi berupaya mencegah atau mengurangi laju perubahan iklim, sedangkan adaptasi berupaya menyesuaikan diri dengan dampak yang sudah terjadi atau tidak dapat dihindari. Keduanya sangat penting untuk menghadapi tantangan perubahan iklim secara komprehensif.
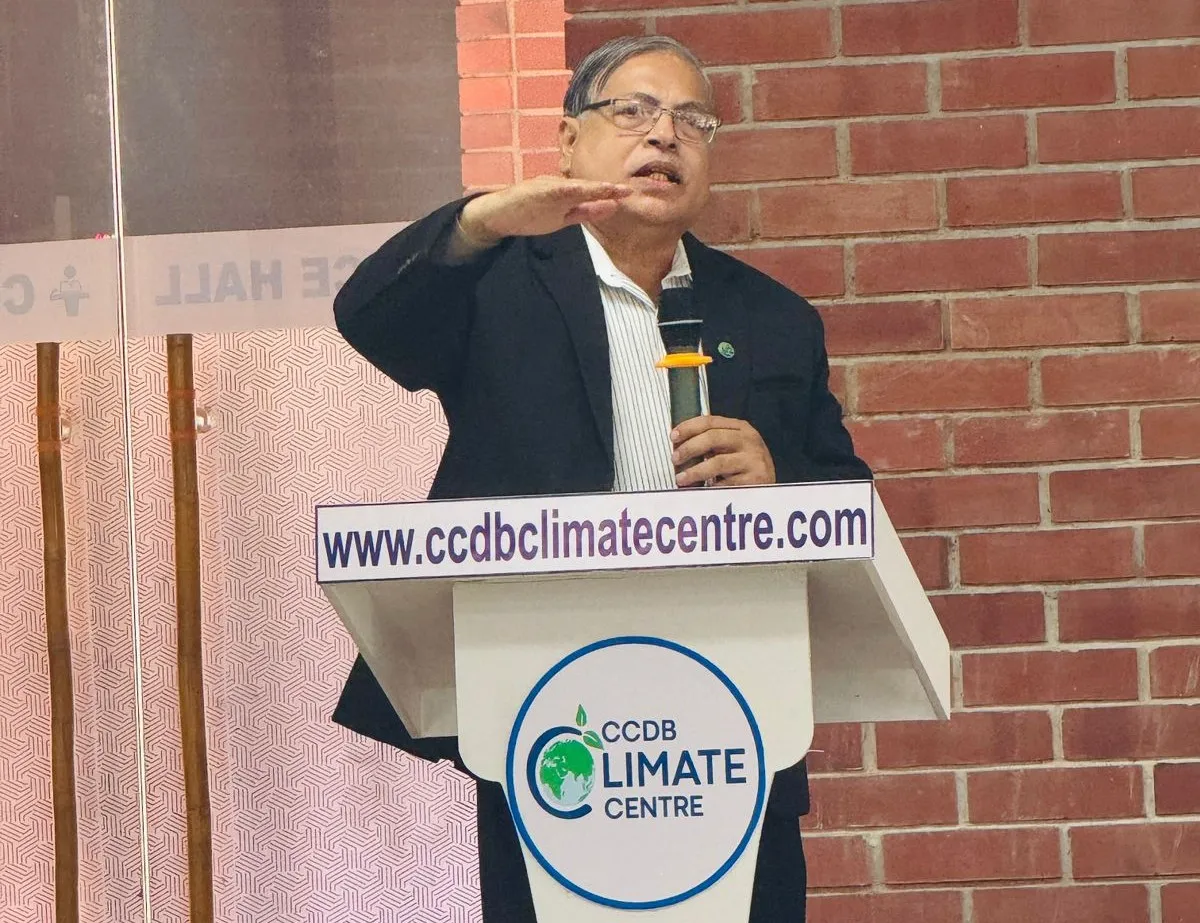
Menurut Ahmed, adaptasi belum mendapat perhatian sebesar mitigasi, padahal ancaman perubahan iklim sudah di depan mata. Fenomena banjir, kenaikan muka air laut, hingga gagal panen sudah dirasakan langsung oleh masyarakat di negara-negara rentan. Tanpa dukungan adaptasi, beban sosial dan ekonomi akan semakin berat.
Dalam presentasinya, Ahmed menjelaskan bahwa mitigasi memang penting untuk menekan emisi gas rumah kaca, tetapi adaptasi menyangkut kesiapan menghadapi dampak yang tidak bisa dihindari. Ia menekankan, strategi adaptasi harus berjalan beriringan dengan mitigasi agar dunia lebih tangguh menghadapi krisis iklim.
Data terbaru menunjukkan mayoritas dana global justru terserap pada proyek energi dan transportasi. Sebaliknya, proyek adaptasi masih kurang diminati, baik oleh pemerintah maupun investor swasta. Padahal, di banyak wilayah Asia-Pasifik, kebutuhan adaptasi semakin mendesak untuk melindungi kehidupan masyarakat sehari-hari.
Ahmed menilai, investasi dalam adaptasi lebih dekat dengan kepentingan manusia. Contoh nyata adalah pembangunan tanggul di daerah pesisir, penyediaan air bersih di wilayah rawan kekeringan, hingga memperkuat sistem kesehatan menghadapi penyakit yang menyebar akibat perubahan iklim.
Ia juga menyinggung bahwa sejak 2003, proyek mitigasi jauh lebih dominan dibanding adaptasi di kawasan Asia-Pasifik. Pola kebijakan dan pendanaan yang berat sebelah ini dinilai berpotensi memperburuk risiko, sebab masyarakat tidak disiapkan secara memadai menghadapi dampak perubahan iklim.
Dalam paparannya, Ahmed mengingatkan bahwa adaptasi tidak melulu soal infrastruktur. Pengetahuan lokal, kearifan masyarakat, serta tata kelola yang inklusif juga menjadi bagian penting dari strategi bertahan. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah, akademisi, organisasi sipil, dan komunitas lokal sangat dibutuhkan.
Pemerintah, menurutnya, harus berani mengambil peran melalui kebijakan yang berpihak pada adaptasi. Regulasi tata ruang, insentif inovasi hijau, hingga perlindungan sosial bagi kelompok rentan bisa menjadi langkah konkret yang memperkuat ketahanan masyarakat.
Selain pemerintah, sektor swasta juga memiliki kontribusi besar. Dunia usaha dapat menyesuaikan model bisnis mereka dengan risiko iklim, sekaligus menghadirkan solusi yang membantu masyarakat. Skema asuransi untuk petani yang gagal panen akibat cuaca ekstrem menjadi salah satu contoh produk yang relevan.
Ahmed menekankan bahwa pendanaan adaptasi tidak seharusnya hanya berbasis utang. Negara-negara maju perlu menepati janji hibah iklim sebesar 100 miliar dolar AS per tahun yang disepakati sejak 2009. Dana tersebut idealnya lebih proporsional dialokasikan untuk adaptasi, bukan hanya mitigasi.
Ia juga menegaskan pentingnya langkah adaptasi di tingkat komunitas. Meski berskala kecil, langkah sederhana seperti pola tanam yang menyesuaikan iklim atau pengelolaan sumber air bersama mampu memperkuat daya tahan masyarakat. Jika dilakukan konsisten, langkah ini bisa memberi dampak besar.
Kesenjangan informasi menjadi salah satu hambatan. Tidak semua komunitas memiliki akses terhadap data iklim atau teknologi yang memadai. Karena itu, Ahmed menilai kerja sama lintas negara dan lembaga sangat penting agar pengetahuan dan teknologi dapat menjangkau masyarakat paling rentan.
Dalam kerangka keadilan iklim, Ahmed mengingatkan bahwa negara-negara yang paling sedikit menyumbang emisi justru sering kali menanggung dampak paling parah. Dengan memperkuat adaptasi, dunia menunjukkan kepedulian bahwa keadilan lingkungan harus diwujudkan dalam praktik, bukan sekadar janji.
Lebih jauh, adaptasi dipandang sebagai peluang untuk membangun masa depan berkelanjutan. Investasi di bidang pertanian tahan iklim, kota hijau, hingga energi terbarukan lokal bukan hanya memperkuat ketahanan, tetapi juga membuka lapangan kerja baru.
Kebijakan Pemerintah Indonesia
Sama halnya dengan negara lain, Indonesia menghadapi tantangan besar akibat perubahan iklim. Data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat sejak 1981 hingga 2018 suhu rata-rata di Indonesia naik sekitar 0,03 derajat Celsius setiap tahun. Sementara itu, data Bappenas tahun 2021 menunjukkan kenaikan muka laut sebesar 0,8 hingga 1,2 sentimeter per tahun, padahal 65 persen penduduk Indonesia tinggal di wilayah pesisir.
Kondisi ini membuat upaya adaptasi menjadi kebutuhan mendesak. Pemerintah berkomitmen menyiapkan langkah nyata agar masyarakat tetap tangguh menghadapi dampak iklim yang makin terasa. Salah satu strategi yang dilakukan adalah menerapkan Climate Budget Tagging (CBT), yakni penandaan anggaran khusus untuk mitigasi dan adaptasi iklim dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Mekanisme ini mulai dijalankan sejak 2016 dan terus diperkuat. Dalam sistem tersebut, pemerintah mengalokasikan kode anggaran tersendiri untuk adaptasi. Anggaran ini difokuskan pada peningkatan ketahanan ekonomi, sosial, dan ekosistem. Tujuannya, mengurangi kerugian yang ditimbulkan akibat perubahan iklim, seperti kerusakan infrastruktur, penurunan hasil pertanian, hingga kerentanan kesehatan masyarakat.
Rata-rata belanja untuk aksi iklim sejak 2016 hingga 2022 mencapai Rp81,3 triliun per tahun atau sekitar 3,5 persen dari total APBN. Persentase ini bahkan lebih tinggi dibanding mayoritas negara lain.
Melalui CBT, setiap kementerian dan lembaga dapat lebih mudah mengidentifikasi apakah program yang mereka jalankan berkontribusi terhadap adaptasi iklim. Misalnya, proyek yang meningkatkan ketahanan pangan, memperkuat layanan kesehatan, atau melindungi ekosistem pesisir dapat masuk ke dalam kategori adaptasi.
Pemerintah berharap, penandaan anggaran ini mendorong transparansi, keterlibatan pemangku kepentingan, serta memastikan alokasi dana adaptasi benar-benar digunakan secara efektif. Dengan begitu, upaya adaptasi tidak lagi bersifat seremonial, melainkan betul-betul menyentuh kebutuhan masyarakat yang paling rentan terhadap dampak iklim.
Apa yang Bisa Dilakukan Masyarakat
Adaptasi perubahan iklim selama ini kerap dipandang sebagai urusan besar: konferensi global, komitmen negara-negara, pendanaan hingga miliaran rupiah dari anggaran pemerintah dan swasta. Padahal, di balik usaha global tersebut, ada peran masyarakat lokal yang sama pentingnya. Adaptasi tidak hanya lahir dari keputusan politik, tetapi juga dari tindakan sederhana yang dilakukan sehari-hari di rumah, lahan pertanian, hingga lingkungan sekitar.
Kenyataannya, dampak perubahan iklim sudah nyata terasa di Indonesia. Suhu yang terus meningkat, musim yang tak menentu, hingga kenaikan permukaan laut menjadi tantangan bagi banyak orang. Meski pemerintah menyiapkan mekanisme anggaran khusus adaptasi, daya tahan bangsa ini juga ditentukan oleh kesadaran warganya untuk ikut menyesuaikan diri.

Di kota Bandung, misalnya, sebagai bentuk konkret adaptasi perubahan iklim, warga RW 19 Antapani Tengah, membangun kawasan bebas sampah melalui pengolahan terintegrasi di Jasmine Integrated Farming sejak 2020. Dengan mengelola sampah organik menggunakan metode modern serta memaksimalkan bank sampah untuk sampah anorganik, kawasan ini mampu menekan beban pengiriman ke TPA hingga satu ton per minggu. Upaya ini tidak hanya mengurangi emisi dari sampah, tetapi juga menghadirkan model urban farming yang memberi manfaat sosial, ekonomi, dan lingkungan, sekaligus menjadi contoh nyata bagaimana masyarakat dapat beradaptasi menghadapi krisis iklim melalui solusi lokal yang berkelanjutan.
Sementara itu, Yayasan Odesa melalui program filantropinya memiliki banyak program untuk adaptasi perubahan iklim ini. Salah satunya pemulihan lingkungan di Kecamatan Cimenyan yang termasuk Kawasan Bandung Utara. Tantangan besar yang mereka hadapi adalah kondisi tanah gersang, yang sering disebut “tanah sakit” karena sulit ditanami. Odesa menawarkan solusi agroekologi dengan budidaya tanaman hanjeli, tanaman yang mampu tumbuh di lahan marginal sekaligus memperbaiki struktur tanah agar kembali subur. Inisiatif ini bukan hanya menghidupkan kembali lahan kritis, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan masyarakat, sehingga menjadi langkah nyata menghadapi dampak perubahan iklim secara berkelanjutan.

Adaptasi berbasis komunitas terbukti efektif di banyak tempat. Dua Tindakan kongkret di atas contoh gotong royong menghadapi iklim yang makin sulit diprediksi dan tak bisa dicegah.
Semua upaya sederhana ini jika digabungkan akan melengkapi kebijakan dan pendanaan besar pemerintah. Adaptasi bukan semata urusan global, melainkan tanggung jawab bersama yang berawal dari rumah dan lingkungan sekitar. (*)























