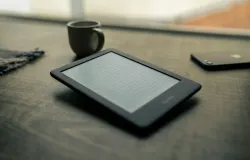Dalam sejarah panjang manusia, agama sering dipahami sebagai sesuatu yang mapan, sistem keyakinan besar dengan kitab suci, lembaga, dan pengikut yang luas. Namun, di balik cerita arus utama itu, ada banyak tradisi lain yang lahir dari keresahan sosial, dari jeritan ketidakadilan, dan dari keberanian untuk menantang tatanan yang dianggap harmoni.
Mereka tidak selalu bertahan dalam bentuk besar dan terorganisir, sebagian justru ditekan, disisihkan, atau dilupakan. Tetapi jejaknya masih bergema, menawarkan pelajaran penting tentang religiusitas yang bisa bersuara sebagai kritik sosial.
Den Mazdak
Pada abad ke-5 M, Kekaisaran Sassaniyah berdiri di atas jurang ketimpangan. Kaum bangsawan dan magi Zoroastrian hidup dalam kemewahan, sementara rakyat jelata dicekik kemiskinan. Dari kegelisahan sosial ini, muncul sosok karismatik bernama Mazdak. Ia bukan hanya seorang reformator, tetapi juga visioner yang berani melahirkan agama dengan cita-cita egalitarian.
Sejarawan Ehsan Yarshater dalam “Mazdakism” (The Cambridge History of Iran, Vol. 3(1), 1983) menegaskan bahwa inti ajaran Mazdak bertumpu pada empat pilar. Ialah komunalisme harta, revolusi dalam struktur keluarga, dualisme kosmik antara cahaya dan kegelapan, serta pasifisme radikal yang menolak kekerasan. Dengan kata lain, agama Mazdak adalah upaya radikal untuk mengubah struktur sosial, menggeser agama dari altar elit ke ruang hidup rakyat alit.
Didukung Raja Kavad I, gagasan ini menemukan tanah subur di kalangan petani, pengrajin, dan kaum miskin.
Mereka melihat Mazdak sebagai jalan “agama keadilan” yang memberi harapan baru. Namun, radikalisme yang menentang privilese elit akhirnya mengundang murka penguasa. Di bawah Khusraw Anushirvan, Mazdak dan ribuan pengikutnya dibantai.
Meski begitu, api yang sempat dinyalakan tidak padam sepenuhnya. Pada periode Islam awal, prinsip kolektivisme dan persaudaraan Mazdak masih hidup dalam komunitas Khurramis dan Qarmatis, dari desa-desa di Kufa hingga kota Lahsa abad ke-11. Di sana, harta dikumpulkan bersama, kebutuhan dipenuhi kolektif, dan kehidupan sosial diatur demi menegakkan keadilan.
Gerakan Sramana
Berabad-abad sebelum itu, di tanah India abad ke-6 sebelum masehi, altar-altar Brahmana dipenuhi api kurban, simbol dari dominasi ritual dan hirarki kasta. Namun dari balik asap dupa dan mantra, lahir sekelompok pengembara rohani yang memilih jalan berbeda. Mereka disebut Sramana, para “pengupas diri”, yang mencari kebenaran bukan dalam ritus dan kitab suci, melainkan dalam pengalaman, hening meditasi, dan disiplin batin.
Menurut Anish Chakravarty (2022) dalam “Sañjaya Belaṭṭhiputta and the Ancient Śramaṇa Tradition”, gerakan ini membawa semacam demokratisasi spiritual. Pencerahan tidak lagi dianggap hak eksklusif Brahmana, melainkan mungkin bagi tiap orang, termasuk perempuan, petani, atau bahkan pelacur. Kisah Ambapali, sang penari istana, dan Sujata, gadis desa sederhana, menjadi penanda bahwa cahaya kebenaran bisa singgah di hati siapa saja yang tulus mencarinya.
Sramana bukanlah tradisi tunggal. Johannes Bronkhorst dalam “Greater Magadha: Studies in the Culture of Early India” (2007) melihatnya sebagai hutan yang rimbun dengan jalur-jalur berliku. Di dalamnya hidup Jain yang menekankan asketisme ketat dan ahimsa mutlak, Ajivika yang percaya pada determinisme kosmik, dan Buddha yang meramu jalan tengah dengan menolak keabadian diri serta menawarkan Nirvana sebagai kebebasan sejati.
Di tepi hutan itu, suara lebih liar bergema. Carvaka atau Lokayata dengan materialisme ateistiknya yang menolak karma dan reinkarnasi, atau Ajnyana yang membawa skeptisisme hingga meruntuhkan segala kepastian.
Sramana tidak hanya mengguncang altar, tetapi juga singgasana.
Mereka menolak akumulasi kekayaan oleh elit dan menantang dogma yang membenarkan ketidakadilan. Dukungan raja-raja seperti Bimbisara dan Ajatashatru menunjukkan bahwa pengaruh mereka mampu melemahkan monopoli Brahmana. Dengan begitu, Sramana tidak sekadar jalan pertapaan, melainkan juga gerakan sosial yang menjadikan kesadaran sebagai senjata dan kebajikan sebagai perlawanan.
Mo Jia
Di tengah pergulatan Tiongkok zaman Negara-Negara Berperang (abad ke-5 SM), ketika ritual mewah dan upacara kerajaan menjadi alat kaum elit untuk meneguhkan kuasa, muncullah Mozi, seorang guru yang menantang arus. Bagi Mozi keadilan sosial tidak lahir dari musik istana atau pemakaman megah, melainkan dari kesederhanaan, kerja keras, dan kasih universal.
Chris Fraser dalam “The Philosophy of the Mozi: The First Consequentialists” (2016) menekankan bahwa Mo Jia berakar pada religiusitas yang kuat. Mozi melihat Tian, Sang Langit sebagai otoritas moral tertinggi yang mengawasi manusia. Langit menghendaki cinta yang merata, tanpa pilih kasih, sehingga tugas manusia adalah menata hidup sesuai perintah kosmik ini.
Namun Mo Jia tidak berhenti pada ajaran, ia membentuk komunitas yang disiplin, semacam “ordo tanpa biara” yang hidup sederhana, siap menolong rakyat miskin, bahkan berani menghadapi tirani. Ritus pun tetap ada, meski dibersihkan dari kemewahan.
Misal pemakaman secukupnya, penghormatan roh tanpa pemborosan, dan pengorbanan diganti dengan kesalehan praktis.
Dengan cara ini, Mo Jia berdiri sebagai agama-etika alternatif. Ia tidak mengajarkan keselamatan yang rumit di alam baka, tapi menegakkan keadilan di bumi. Ia juga tidak memuja musik dan persembahan mahal, tapi mengajarkan cinta universal dan solidaritas sosial. Dalam dunia yang retak oleh perang dan ketidakadilan, Mozi mengubah poros Tiongkok terhadap Langit dan roh menjadi dasar moral bagi masyarakat egaliter.
Rastafari
Berabad-abad kemudian, jauh di seberang lautan, sebuah gerakan religius lahir dari luka kolonialisme dan perbudakan. Rastafari muncul di Jamaika pada awal abad ke-20, sebagai jawaban atas penindasan rasial, kemiskinan, dan pencarian identitas religius kaum keturunan Afrika di Karibia.
Vivaldi Jean-Marie dalam “An Ethos of Blackness: Rastafari Cosmology, Culture, and Consciousness” (2023) menekankan bahwa Rastafari adalah lebih dari sekadar musik atau gaya hidup. Ia adalah kosmologi pembebasan. Bagi pengikutnya, Haile Selassie I, kaisar Ethiopia, adalah manifestasi ilahi, simbol kemenangan Afrika atas kolonialisme Eropa.
Akar Rastafari terletak pada gagasan Zion dan Babilon. Zion berarti tanah kebebasan, spiritual maupun nyata, yang diwujudkan dalam visi kembali ke Afrika. Babilon adalah simbol sistem penindasan, kapitalisme, dan supremasi kulit putih.
Dengan bahasa simbolik ini, Rastafari membentuk kritik tajam terhadap tatanan global.
Ritual mereka sederhana tapi penuh makna. Nyanyian nyabinghi, doa, pembacaan Alkitab dalam tafsir Afrosentris, dan penggunaan ganja sebagai medium menyatukan tubuh, roh, dan komunitas. Musik reggae menjadi corong global ajaran ini, terutama lewat Bob Marley, yang menjadikan Rastafari identik dengan perlawanan damai dan solidaritas lintas bangsa.
Meski sering dianggap pinggiran, Rastafari membalikkan narasi agama. Ia menegaskan bahwa Ilahi bisa berpihak pada kaum miskin dan terjajah, bahwa religiusitas bisa tumbuh dari musik, komunitas, dan identitas kulit hitam.
Refleksi
Apa yang kita baca di sini hanyalah sekelumit dari lautan tradisi religius yang ada di dunia. Masih banyak agama dan gerakan serupa lainnya, besar maupun kecil, populer maupun tersisih, yang lahir dari keresahan sosial dan dari dorongan untuk menegakkan keadilan.
Suara-suara itu mungkin tidak pernah terdengar oleh arus utama sejarah, tetapi jejaknya tetap hidup, membentuk cara manusia memahami diri, komunitas, dan dunianya hingga hari ini.
Baca Juga: Jain dan Sunda di Restoran 'Hijau' Bandung
Setiap tradisi memiliki keunikan dan lanskapnya sendiri, baik dalam ritual, etika, keyakinan, maupun cara melihat dunia. Tidak ada satu format dominan yang bisa mewakili semuanya. Membaca agama-agama ini melalui kerangka yang sama dengan agama besar bisa menutupi kedalaman dan karakter spesifiknya.
Dan dari sini kita belajar bahwa religiusitas kadang bukan hanya soal doktrin atau ritual, tetapi tentang keberanian menegakkan pembebasan. Tentu dengan memandang bahwa setiap tradisi punya caranya sendiri-sendiri. Dunia masih penuh dengan narasi-narasi semacam itu, menunggu untuk ditemukan, didengar, dan dipahami. (*)