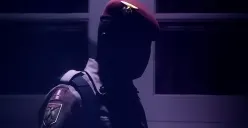Pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, termasuk Jawa Barat, sebesar sekitar Rp2,4 triliun pada triwulan terakhir tahun ini menjadi kabar yang mengguncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terdengar seperti langkah teknokratis biasa dalam menjaga stabilitas fiskal nasional.
Namun bagi pemerintah daerah, terutama di Jawa Barat yang memiliki belanja tinggi dan ketergantungan besar terhadap dana pusat, ini adalah ujian serius. Ujian terhadap tata kelola, prioritas kebijakan, bahkan kepemimpinan dalam mengelola krisis anggaran.
Di banyak ruang rapat pemerintahan daerah, topik yang tadinya berkisar pada “target kinerja” dan “proyek strategis” tiba-tiba bergeser ke satu pertanyaan: “mana yang harus dipangkas lebih dulu?” Situasi ini menunjukkan betapa rentannya sistem fiskal daerah yang selama dua dekade desentralisasi belum sepenuhnya mandiri. Daerah seperti Jawa Barat, meski menjadi salah satu motor ekonomi nasional, masih bergantung pada pusat dalam proporsi yang terlalu besar.
Dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Barat, sekitar 65 persen pendapatan masih berasal dari transfer pemerintah pusat, baik dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), maupun Dana Bagi Hasil (DBH). Ketika pusat melakukan penyesuaian karena tekanan fiskal nasional, ruang gerak daerah langsung menyempit. Di titik inilah pentingnya membicarakan ulang apa arti kemandirian fiskal bagi provinsi sebesar Jawa Barat.
Efisiensi adalah kata yang terdengar indah di atas kertas. Tapi di lapangan, ia sering berwajah paradoks. Saat pemerintah provinsi mulai memangkas anggaran perjalanan dinas, biaya makan-minum rapat, hingga kegiatan seremonial, publik menyambut positif. Namun tidak sedikit pejabat teknis yang gelisah, karena beberapa kegiatan yang terkena dampak pemangkasan justru berkaitan dengan program pelayanan publik yang strategis.
Pemerintah daerah kini berada di persimpangan. Di satu sisi, efisiensi menjadi keharusan moral dan politik. Tapi di sisi lain, pelayanan publik tak bisa berhenti. Pemotongan belanja yang tidak cermat bisa menimbulkan efek domino: layanan kesehatan yang tertunda, proyek infrastruktur kecil yang mandek, atau kegiatan pemberdayaan masyarakat yang tak jadi dijalankan. Efisiensi yang salah arah bisa berubah menjadi kontraproduktif.
Itulah sebabnya, langkah Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang meninjau ulang seluruh pos anggaran rutin patut diapresiasi, selama prosesnya berbasis pada budget impact analysis, bukan sekadar pemangkasan merata. Setiap rupiah yang dikeluarkan pemerintah harus mampu menjawab satu pertanyaan sederhana: “apa dampaknya bagi publik?”
Kita memerlukan budaya baru dalam perencanaan fiskal: mengalokasikan bukan karena tradisi, tapi karena kebutuhan; menghemat bukan karena terpaksa, tapi karena sadar dampak.
Krisis fiskal yang tengah dihadapi Jawa Barat sebenarnya bisa menjadi momentum untuk menata ulang cara daerah ini berpikir tentang uang dan pembangunan. Di tengah tekanan anggaran, justru terbuka peluang untuk melahirkan reformasi fiskal yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan. Selama ini, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Barat sebagian besar masih bergantung pada tiga sumber klasik: pajak kendaraan bermotor, bea balik nama, dan pajak air permukaan. Ketiganya penting, tetapi tidak cukup untuk menopang ambisi pembangunan daerah sebesar Jawa Barat.
Padahal, ruang inovasi masih terbentang luas. Digitalisasi pajak dan retribusi daerah, misalnya, bisa menjadi tonggak perubahan. Dengan sistem yang lebih terintegrasi, pemerintah daerah dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus memperkuat transparansi. Integrasi data pajak dengan perbankan, layanan transportasi daring, hingga e-commerce akan membuka cakrawala baru bagi penerimaan daerah. Tanpa menaikkan tarif atau menambah beban masyarakat, potensi pajak bisa digali dari aktivitas ekonomi yang selama ini luput dari radar fiskal.
Beberapa kota di dunia bahkan telah mempraktikkan micro-levy system untuk transaksi digital lokal. Dalam sistem itu, setiap kali warga melakukan transaksi daring, sebagian kecil biayanya otomatis dikembalikan untuk pembangunan wilayah misalnya untuk perbaikan trotoar, taman kota, atau digitalisasi layanan publik. Nilainya kecil, tetapi jika dikumpulkan secara konsisten, hasilnya signifikan. Prinsipnya sederhana: pembangunan dibiayai oleh aktivitas ekonomi masyarakat secara kolektif, bukan oleh pajak yang memberatkan.
Selain digitalisasi fiskal, sektor-sektor dengan potensi ekonomi tinggi seperti pariwisata, ekonomi kreatif, dan energi baru terbarukan juga bisa menjadi mesin baru bagi PAD Jawa Barat. Dengan lanskap alam dan budaya yang beragam, Jawa Barat seharusnya bisa melampaui model pembangunan konvensional yang hanya bergantung pada dana pusat. Jika dikelola dengan kebijakan insentif yang cerdas seperti pembebasan pajak untuk investasi ramah lingkungan, atau dukungan modal bagi usaha kreatif lokal daerah. Hal tersebut bisa menjadi episentrum inovasi ekonomi hijau di Indonesia.
Sayangnya, banyak daerah masih terjebak dalam cara lama: menunggu transfer dari pusat, bukan mencipta sumber dari potensi sendiri. Paradigma ini sudah saatnya diubah. Pemerintah daerah harus berani keluar dari zona nyaman birokrasi yang reaktif dan mulai berpikir sebagai institusi penggerak ekonomi. Di sinilah makna sejati kemandirian fiscal, bukan sekadar soal menambah pendapatan, tetapi tentang membangun keberanian untuk menentukan arah pembangunan sendiri.
Tiga Agenda Utama Reformasi Fiskal

Dalam jangka menengah, reformasi fiskal Jawa Barat perlu diarahkan pada tiga agenda utama. Pertama, memperluas basis pendapatan daerah melalui inovasi kebijakan yang berpihak pada produktivitas dan kreativitas masyarakat. Kedua, memperkuat efisiensi belanja dengan pendekatan digital budgeting, di mana setiap rupiah yang keluar dapat dilacak dampaknya, bukan sekadar dilaporkan penggunaannya. Ketiga, membangun kolaborasi lintas sektor melalui skema public-private partnership (PPP) yang berorientasi pada akuntabilitas publik.
PPP seringkali disalahpahami sebagai bentuk penyerahan tanggung jawab negara kepada swasta. Padahal, konsep dasarnya justru menempatkan pemerintah sebagai pengatur manfaat publik yang strategis. Negara mengarahkan sumber daya swasta untuk berkontribusi pada pembangunan sosial, bukan sekadar mengejar profit. Jika dikelola dengan prinsip keterbukaan dan keseimbangan, PPP dapat menjadi jembatan antara kebutuhan pembangunan yang besar dan keterbatasan fiskal yang nyata.
Kemandirian fiskal Jawa Barat tidak akan lahir dari kelimpahan dana, melainkan dari keberanian untuk berinovasi di tengah keterbatasan. Krisis fiskal hari ini bisa menjadi batu loncatan menuju sistem keuangan daerah yang lebih adaptif, transparan, dan berdaya tahan. Ia menuntut kepemimpinan yang mampu memadukan ketegasan teknokratis dengan keberanian moral, untuk mengubah pola pikir birokrasi dari sekadar mengelola uang menjadi menciptakan nilai dari setiap rupiah yang ada.
Isu kemandirian fiskal sering dibahas dari sisi teknokratis, padahal akar masalahnya juga politis. Selama daerah masih bergantung pada pusat untuk bertahan hidup, kedaulatan politik daerah akan selalu terbatas. Daerah sulit mengambil kebijakan berani jika setiap langkahnya ditentukan oleh jadwal pencairan transfer.
Kemandirian fiskal adalah syarat dasar bagi kemandirian kebijakan. Pemerintah daerah yang kuat secara fiskal lebih mampu menolak kebijakan populis yang tidak rasional dan sebaliknya berani berinvestasi pada kebijakan jangka panjang, seperti reformasi pendidikan, riset, dan lingkungan.
Untuk mencapai titik itu, reformasi fiskal tidak bisa hanya berhenti di pemerintah provinsi. Pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat juga perlu bertransformasi. Banyak daerah dengan potensi PAD besar justru belum optimal karena tata kelola yang tertutup atau infrastruktur data fiskal yang lemah. Transparansi menjadi kunci. Daerah yang membuka data anggarannya secara publik terbukti memiliki tingkat kepercayaan yang lebih tinggi dari masyarakat dan investasi yang lebih stabil.
Pemotongan dana transfer adalah ujian kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Publik akan menilai bukan dari besarnya potongan, melainkan dari cara pemerintah mengelola dampaknya. Jika efisiensi dijalankan tanpa komunikasi yang baik, publik bisa salah paham dan menilai pemerintah sedang mengurangi perhatian terhadap masyarakat.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat perlu mengedepankan komunikasi yang jujur dan terbuka. Penjelasan tentang apa yang dipangkas, kenapa, dan bagaimana dampaknya terhadap layanan publik harus disampaikan dengan data, bukan jargon. Masyarakat berhak tahu bahwa penghematan anggaran bukan berarti penurunan pelayanan, melainkan perbaikan cara kerja.
Inilah pentingnya narasi fiskal. Di tengah turbulensi ekonomi global, masyarakat butuh diyakinkan bahwa setiap rupiah pajak yang mereka bayarkan digunakan dengan bertanggung jawab. Ketika komunikasi fiskal dibangun dengan empati dan transparansi, kebijakan yang sulit pun bisa diterima dengan lebih lapang.
Dalam sejarahnya, Jawa Barat sering menjadi laboratorium kebijakan nasional. Dari inovasi pelayanan publik hingga penataan birokrasi, banyak praktik baik lahir dari provinsi ini. Krisis fiskal kali ini bisa menjadi pelajaran berharga untuk membangun paradigma baru pengelolaan keuangan daerah yang lebih adaptif dan berkelanjutan.
Jawa Barat punya kapasitas intelektual, infrastruktur digital, dan basis sosial yang kuat untuk menjadi pelopor fiscal innovation region di Indonesia. Tapi itu hanya bisa terjadi jika ada kemauan politik yang konsisten, keberanian untuk meninggalkan cara lama, menolak pemborosan, dan memperjuangkan akuntabilitas.
Pemotongan dana transfer pusat mungkin hanya berlangsung sementara, tapi pesan yang dibawanya bersifat permanen: daerah harus berani mandiri. Tanpa kemandirian fiskal, otonomi daerah hanya akan menjadi slogan administratif.
Kemandirian fiskal bukan semata urusan angka, melainkan refleksi kematangan demokrasi. Daerah yang mampu mengatur sumber dayanya sendiri adalah daerah yang benar-benar berdaulat. Dalam konteks ini, Jawa Barat sedang diuji. Mampukah ia mengubah tekanan menjadi kesempatan, keterbatasan menjadi inovasi?
Ujian ini bukan hanya milik pemerintah, tapi juga milik masyarakat. Karena pada akhirnya, yang diuji bukan sekadar kemampuan mengelola anggaran, melainkan kemampuan membangun kepercayaan, menjaga solidaritas, dan menegakkan integritas di tengah krisis. (*)