Bayangkan suatu dunia di mana pikiran bukan lagi sekadar gelombang listrik yang terkurung dalam tengkorak, melainkan entitas yang bisa disimpan, dikirim, bahkan diwariskan seperti harta benda. Di mana kenangan masa kecil yang mulai kabur bisa diputar ulang dengan presisi tinggi, atau di mana seorang penyandang disabilitas bisa menggerakkan lengan robot hanya dengan berpikir.
Inilah janji Neuralink, sebuah terobosan yang mengaburkan batas antara biologi dan teknologi, antara manusia dan mesin.
Tapi di balik potensinya yang revolusioner, ada pertanyaan filosofis yang menggantung: Apakah kita sedang menciptakan alat untuk memperluas kesadaran, atau justru mengubah esensi manusia menjadi sesuatu yang lain?
Neuralink mengandaikan otak seperti komputer: jaringan saraf adalah hardware, sementara pikiran dan ingatan adalah software yang bisa diunduh atau diunggah. Analogi ini menarik, tapi sekaligus problematis.
Otak manusia bukanlah sirkuit statis, ia organ yang dinamis, terus berubah berdasarkan pengalaman, emosi, bahkan kerusakan fisik. Jika suatu chip bisa "membaca" atau "menulis" sinyal otak, apakah ia benar-benar memahami makna di baliknya? Atau ia hanya memindahkan data tanpa konteks, seperti mesin penerjemah yang lancar berbahasa, tapi tak pernah paham keindahan puisi?
Di sini, pemikiran Ibnu Rusyd tentang akal praktis dan teoritis relevan. Akal praktis—yang terkait dengan pengalaman sehari-hari—mungkin bisa direplikasi oleh algoritma. Tapi akal teoritis, yang abstrak dan melampaui materi, barangkali tetap menjadi ranah eksklusif kesadaran manusia. Neuralink bisa jadi alat bantu, tapi tidak menggantikan jiwa yang berpikir.
Kenangan sebagai Komoditas
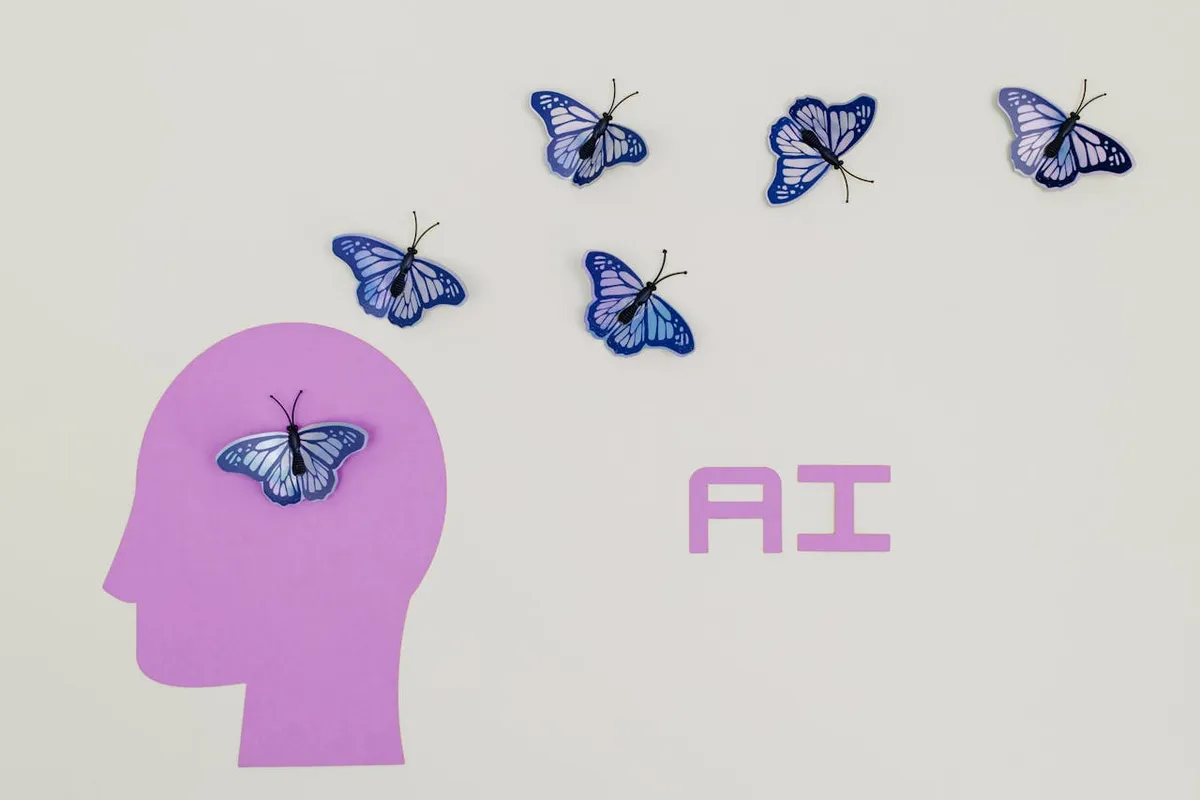
Bayangkan pasar di mana kenangan indah, seperti wisuda, pernikahan, bahkan momen spiritual, bisa dibeli dan dijual. Atau sebaliknya: trauma bisa dihapus seperti menghapus file korup. Ini bukan lagi fiksi; startup seperti Kernel sudah mengeksplorasi brain-data monetization. Tapi di baliknya ada bahaya distopia: jika ingatan bisa dimanipulasi, apa yang tersisa dari "diri" yang otentik?
Dalam Black Mirror, karakter yang kecanduan memutar ulang kenangan justru terperangkap dalam masa lalu. Ini peringatan: teknologi yang dirancang untuk membebaskan bisa menjadi penjara baru. Seperti kata Nietzsche, "Kita perlu melupakan untuk bisa bertindak."
Era digital telah mengubah cara kita beragama. Kini ada doa via live streaming, zikir dengan aplikasi, bahkan algoritma yang menyarankan ayat Al-Qur'an berdasarkan mood. Neuralink bisa membawa ini lebih jauh: bagaimana jika pengalaman religius (seperti rasa khusyuk atau "kesatuan dengan Tuhan") bisa distimulasi oleh chip? Apakah ini bentuk baru teknologi transendensi, atau reduksi sakralitas menjadi sekadar stimulasi saraf?
Di sinilah kita butuh kerangka etika yang tangguh. Bukan hanya soal apakah teknologi ini aman?, tapi juga apa yang kita pertaruhkan sebagai manusia? Jika otak bisa di-upgrade seperti smartphone, apakah kita risiko kehilangan kerapuhan dan hal yang justru membuat kita manusiawi?
Antara Singularitas dan Spiritualitas
Elon Musk sering bicara tentang singularitas. Saat kecerdasan buatan telah melampaui manusia. Tapi mungkin pertanyaannya bukan akankah mesin menjadi seperti kita?, melainkan akankah kita menjadi seperti mesin? Neuralink bisa menjadi jembatan menuju itu.
Namun, sejarah menunjukkan: setiap lompatan teknologi (dari mesin cetak hingga internet) tak pernah benar-benar menggantikan manusia. Ia hanya mengubah cara kita menjadi manusia. Mungkin Neuralink akan mengikuti pola serupa: alat yang luar biasa, tapi takkan pernah menggantikan keajaiban kesadaran yang tetap misterius.
Jadi, bayangkan suatu hari, anak cucu kita mungkin akan bertanya: Dulu, bagaimana rasanya berpikir tanpa chip? Seperti kita sekarang bertanya bagaimana orang dulu hidup tanpa internet. Jawabannya mungkin sederhana: "Kami tetap manusia. Hanya saja, kami merasakan pikiran kami sepenuhnya, tanpa perlu mengunduhnya."
Neuralink bukan akhir dari manusia. Ia cermin baru untuk pertanyaan lama: Apa artinya menjadi diri kita sendiri? Dan jawabannya, barangkali, tetap harus dicari bukan dalam kode biner, tapi dalam keheningan akal yang merenung. (*)






























