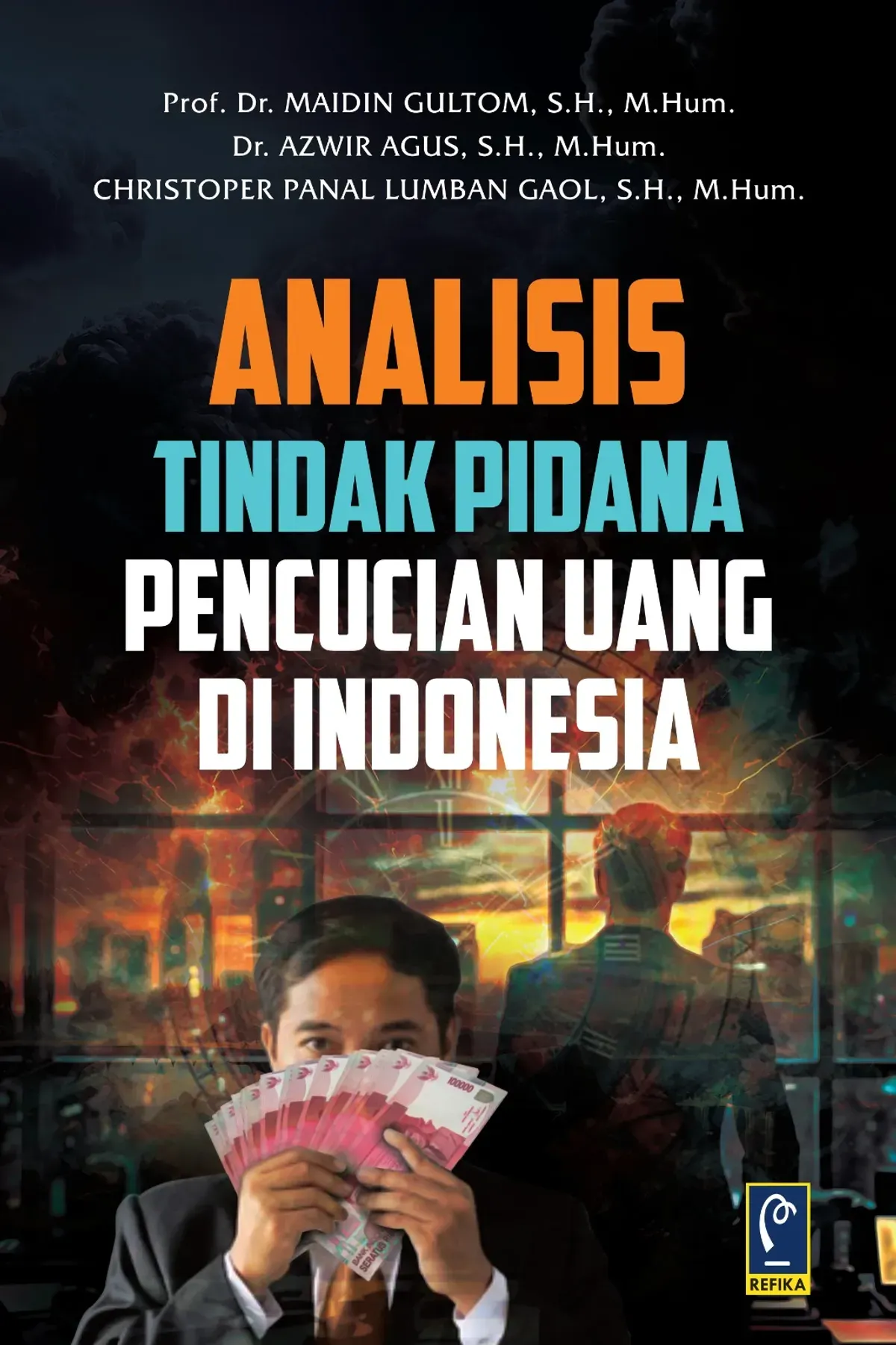Publik dihentikan kasus korupsi di Pemkab Bandung Barat, baru-baru ini, atas pengadaan sarana pandemi Covid-19 kemarin, yang oleh pelaku lantas duitnya "dicuci" dalam aneka aset personal.
Apa yang terjadi ketika uang hasil korupsi, narkotika, atau judi tidak berhenti di tangan pelaku kejahatan, tetapi justru berubah rupa menjadi hotel, vila, atau showroom mobil mewah?
Di sinilah logika pencucian uang bekerja. Tindak pidana ini bukan lagi sekadar cerita kriminal, tetapi telah menjadi seni penyamaran dalam sistem keuangan modern.
Buku Analisis Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia membuka fakta bahwa uang kotor yang semestinya berakhir di pengadilan, justru bisa menyusup ke ruang legal melalui strategi dan celah hukum yang belum sepenuhnya terkunci.
Ditulis oleh Prof. Dr. Maidin Gultom bersama Dr. Azwir Agus dan Christopher Panal Lumban Gaol, buku ini mengajak kita melihat lebih dalam bagaimana praktik pencucian uang masih begitu sulit diberantas di Indonesia.
Sejak awal, pembaca langsung dihadapkan pada kenyataan bahwa praktik ini bukan barang baru. Dari mafia Chicago yang mencuci uang lewat laundry hingga skema investasi properti modern yang merentang antarnegara, intinya tetap sama: menyulap uang hasil kejahatan agar terlihat sah.
Namun, kondisi di Indonesia justru lebih pelik. Bukan karena kita tidak punya undang-undang, tapi karena perangkat yang menegakkan hukum masih tertinggal.
Buku ini menyebutkan bahwa institusi hukum kita kerap sibuk berdebat soal kewenangan ketimbang fokus memburu pelaku. Polisi, jaksa, KPK, bahkan PPATK kerap jalan masing-masing. Koordinasi yang buruk inilah yang membuat banyak kasus pencucian uang mandek di tengah jalan.
Di sisi lain, kecanggihan pelaku kejahatan juga tidak bisa diremehkan. Uang bisa diputar melalui transaksi tunai yang sengaja dipecah, dibelanjakan atas nama orang lain, atau bahkan dibungkus dalam bentuk aset digital.
Yang paling ironis, banyak transaksi mencurigakan lolos begitu saja karena dianggap “hal biasa” oleh masyarakat yang belum paham risiko hukumnya.

Bab demi bab dalam buku ini menguraikan secara sistematis: dari sejarah global money laundering, modus-modus canggih, peran lembaga keuangan, hingga detail celah dalam hukum kita.
Di bab akhir, pembaca diajak menelusuri hambatan struktural seperti birokrasi penyidikan yang lambat dan penyidik yang belum siap dengan kejahatan keuangan berbasis teknologi.
Namun yang membuat buku ini menarik adalah pendekatannya yang tidak sekadar menyodorkan teori.
Penulis membawa pembaca pada contoh konkret, termasuk betapa rumitnya membuktikan niat jahat dalam pencucian uang tanpa jejak digital. Banyak kasus berakhir tanpa kejelasan karena bukti minim dan saksi enggan berbicara.
Apa yang disarankan buku ini tidak muluk. Penulis menekankan bahwa pemberantasan pencucian uang hanya mungkin jika sistemnya dibenahi dari dalam.
Hukum tidak bisa terus tertinggal dari realitas. Dibutuhkan pelatihan rutin, integrasi data antarinstansi, dan edukasi publik agar uang haram tidak terus bebas berkeliaran di pasar yang sah.
Sebagai buku referensi, karya ini tidak hanya penting bagi mahasiswa hukum. Ia relevan juga untuk jurnalis investigasi, pembuat kebijakan, serta publik yang ingin tahu bagaimana uang bisa menghilang dari kejahatan dan muncul kembali di balik kaca bank ternama.
Di tengah meningkatnya kasus korupsi yang makin kompleks dan berselimut rapi, buku ini adalah alarm keras bahwa hukum tidak bisa hanya sekadar mencatat. Ia harus bergerak, mencium jejak, dan menghalangi “sulap” uang kotor itu sejak awal.
Karena pada akhirnya, jika hukum terus kalah cerdas, maka pencucian uang bukan hanya ancaman, tetapi bukti nyata kegagalan kita menjaga keadilan dari balik meja kas. Semoga tak terus begini. (*)