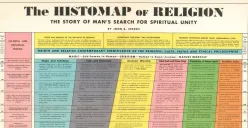Topik kesehatan mental naik daun. Dari obrolan serius di ruang akademik sampai konten receh di media sosial, semua terasa punya pendapat. Menjadi aware soal mental health sekarang bukan cuma tanda kepekaan, tapi juga bagian dari gaya hidup orang muda yang dianggap open minded dan “keren.” Fenomena ini tentu positif, menumbuhkan kesadaran baru tentang kesejahteraan jiwa. Tapi di sisi lain, tren ini juga kadang ditumpangi mereka yang cuma ikut-ikutan tanpa pemahaman yang dalam.
Salah satu isu yang cukup sering muncul di tengah perbincangan kesehatan mental ialah toxic positivity, semangat positif yang justru berbalik menjadi jebakan bagi orang yang sedang terluka. Alih-alih menyembuhkan, sikap ini malah membuat seseorang makin terpuruk karena merasa bersalah telah merasa sedih. Di dalamnya semua emosi negatif dianggap buruk. Mengeluh dipandang lemah. Meski sebetulnya kesedihan dan kerentanan itulah yang menemukan sisi kemanusiaan yang paling jujur.
Masalahnya, toxic positivity sering kali diperkuat oleh pembenaran moral dan bahkan keagamaan. Kalimat seperti “Kamu kurang bersyukur” atau “Itu pasti karma”, sering diucapkan dengan niat baik, tapi malah jadi beban baru bagi orang yang sedang berduka.
Pertanyaannya, benarkah agama-agama mengajarkan bahwa penderitaan adalah kesalahan pribadi atau bukti lemahnya iman? Atau jangan-jangan, itu cuma bias yang menempel pada pemahaman keagamaan kita. Semacam imajinasi sosial yang memaksa semua orang harus always fine demi terlihat beragama?
Carl Olson dalam bukunya Religious Studies: The Key Concepts menjelaskan penderitaan sebagai pengalaman universal dari rasa sakit, baik fisik maupun mental. Ia muncul dari kekerasan, kecemasan, kehilangan, kesepian, ketakutan, bahkan frustasi atas keinginan yang tak terpenuhi. Dalam konteks agama, kata Olson, penderitaan justru mengundang agama-agama untuk hadir. Buat memberi jalan, makna, dan pengharapan dalam menghadapi realitas getir kehidupan. Dari sinilah lahir pertanyaan-pertanyaan eksistensial tentang keadilan, kasih, dan hakikat Ilahi.
Dengan kata lain, penderitaan bukan hanya “masalah” yang harus dihindari, melainkan ruang reflektif tempat agama-agama berbicara paling dalam. Lewat ritus, kisah, doa, dan filsafatnya, agama berupaya memahami dan menuntun manusia menafsirkan derita. Bahkan seringkali, justru dari penderitaanlah agama-agama menemukan bentuk kasih dan kebijaksanaan tertingginya.
Lihat saja bagaimana Buddhadharma memusatkan seluruh ajarannya pada realitas penderitaan (dukkha). Penderitaan dipahami sebagai bagian tak terpisahkan dari keberadaan, bersama dengan ketidakkekalan (anicca) dan ketiadaan diri sejati (anatta). Ketiga hal ini disebut tilakkhana, tiga corak universal kehidupan. Menurut Buddha, penderitaan muncul karena tanha (keinginan atau hasrat) yang didorong oleh tiga racun batin. Ialah keserakahan (lobha), kebencian (dosa), dan kegelapan batin (moha). Selama manusia terikat pada hasrat itu, roda sebab-akibat (kamma) terus berputar. Tapi melalui Jalan Mulia Berunsur Delapan, seseorang bisa belajar melepaskan kemelekatan itu dan mencapai nibbana, kebebasan dari penderitaan.

Dalam tradisi Yahudi, penderitaan juga punya posisi teologis yang kompleks. Ia bisa dipahami sebagai hukuman, tapi juga sebagai sarana pemurnian. Kisah Ayub dalam Tanakh menunjukkan bahwa penderitaan tak selalu berkaitan dengan dosa. Ayub menderita bukan karena kesalahan moral, tapi sebagai kesempatan untuk memahami kebijaksanaan Ilahi yang melampaui logika manusia. Di sini, penderitaan justru membuka ruang dialog antara manusia dan Tuhan. Sebuah dialog yang penuh kejujuran, marah, kecewa, tapi juga keintiman spiritual.
Sementara itu, Kekristenan menempatkan penderitaan pada pusat imannya yakni salib. Yesus Kristus, sosok yang menanggung penderitaan dan kematian, menjadikan salib sebagai simbol teologis yang paradoksal. Tempat pertemuan antara penderitaan terdalam dan kasih terbesar. Sejarah Gereja purba penuh dengan kisah martir, orang-orang yang rela menderita demi iman mereka. Tapi bukan hanya soal heroisme, melainkan kesadaran bahwa dalam penderitaan, manusia bisa turut serta dalam penderitaan Kristus, dan dengan begitu mengalami penebusan yang sejati.
Kosmologi Tiongkok juga punya cara khas memahami derita. Melalui konsep Yin dan Yang, segala hal di dunia dipahami sebagai keseimbangan antara dua kutub yang saling melengkapi. Penderitaan bukan kesalahan kosmos, melainkan bagian dari harmoni alam semesta. Titik hitam di tengah putih yang membuat keseluruhan menjadi utuh. Ajaran Tao mengajarkan wu wei, hidup selaras dengan alam, tidak memaksa, tidak melawan arus kehidupan. Itu bukan sikap apatis, tapi bentuk kebijaksanaan untuk menerima kenyataan sebagaimana adanya, termasuk penderitaan.
Dalam Islam, penderitaan juga dilihat sebagai bagian alami dari perjalanan hidup. Nabi Muhammad sendiri mengalami ‘Aamul Huzni’, “tahun kesedihan,” saat kehilangan orang-orang yang paling dicintainya. Kisah ini memandang Sang Nabi sendiri merupakan sosok yang bisa masuk ke dalam penderitaan. Ia mengalami, ia merasakan. Dan Nabi berpilu batin dalam masa tersebut. Sebuah sisi lain, keteladan yang paling manusiawi.
Dari berbagai religi itu, satu hal jadi jelas. Agama-agama tidak nol empati pada penderitaan. Mereka tidak menafikan luka, tidak selalu menyuruh manusia berpura-pura bahagia. Justru sebaliknya, agama hadir untuk menemani manusia menatap luka itu. Kadang dengan doa, kadang dengan perenungan, kadang dengan penerimaan yang menyakitkan, kadang diam yang mendalam. (*)