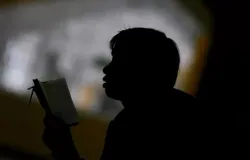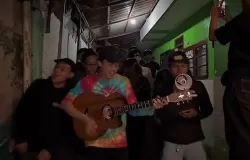MAHASISWA perantau datang ke Kota Kembang Bandung dengan membawa koper dan juga harapan. Mereka mencari kampus, mencari tempat kos, maupun mencari teman. Lantas, tanpa sadar, mereka juga mencari jati diri sendiri.
Bandung menyambut mereka dengan udara yang dulu sejuk, namun sekarang kadang hanya wangi hujan yang tersisa. Jalan-jalan kecil memeluk kaki-kaki bukit yang kian gersang. Dan di sana, langkah-langkah ragu berubah menjadi kebiasaan.
***
Di ruang kuliah, teori-teori berserakan. Di luar ruang kuliah, hidup memberi ujian yang tak ada silabusnya. Nilai akademik diganti dengan nyali.
Kos-kosan adalah laboratorium karakter. Betapa tidak. Mahasiswa belajar hemat. Mereka juga belajar bernegosiasi dengan ibu kos, pun belajar memaknai kata “sendiri”.
Angkot menjadi ruang kuliah bergerak. Sopir, pedagang asongan, dan penumpang lain mengajar pelajaran paling konkret berupa jam kota, ritme kemurahan hati, dan cara menawar.
Dago, Braga, dan Cihampelas menjadi halaman buku yang senantiasa terbuka. Ada tanda tanya di setiap tikungannya. Para mahasiswa membaca lampu-lampu kota seperti membaca catatan kaki.
Di Bandung, kafe bukan semata tempat kongkow dan ngopi. Ia juga adalah ruang aman untuk gagal, untuk mengulang, untuk membahas rasa rindu yang tidak lulus-lulus.
Bahasa Sunda hadir sebagai musik latar. “Mangga.” “Nuhun.” “Hatur nuhun pisan.” Pada mulanya, mungkin mereka malu menirukan. Lama-lama, mereka jatuh hati pada kelembutannya. Someah bukan slogan, tapi cara menyapa dengan ramah dan tulus.
Urusan wisatawan
Turisme Bandung kerap dianggap urusan wisatawan wikenan alias akhir pekan. Padahal, mahasiswa perantau adalah turis untuk jangka panjang. Mereka menjejak pelan Bandung, lebih dalam, dan lebih lama dibanding wisatawan wikenan.
Dalam hal ini, ada turisme emosional yang tumbuh diam-diam dalam wujud sebuah kebiasaan memetakan kota dengan rasa. Contohnya, tempat pertama kali makan seblak sampai keringetan, tempat cinta pertama ditolak, tempat mengabarkan duka lewat telepon, dan sebagainya, dan sebagainya.
Setiap orang membangun “museum personal” di kepalanya. Koleksinya bukan patung atau dokumen, melainkan momen. Contohnya, hujan di depan kampus, senja di Taman Musik, malam romantis di Punclut. Tiket masuknya, dalam hal ini, cuma ingatan.
Ekonomi kota memeluk para mahasiswa rantau. Warung burjo menjadi sponsor utama skripsi. Laundry kiloan menjadi mitra riset tak tertulis.
Ada juga harga yang tak tercantum. Sewa kos naik karena kawasan “instagrammable”. Ruang kampus menyusup ke kafe. Ruang publik menyempit, lalu macet menjadi lagu kojo setempat.
Namun, di tengah komodifikasi, ada solidaritas yang tak dijual. Patungan tiket konser, tebengan pulang, sapaan“Kamu sudah makan?” adalah beberapa contoh dan tata krama sekaligus pertolongan pertama.
Bandung mengajari pelan-pelan bahwa identitas tidak dibangun oleh citra. Ia bertumbuh dari kebiasaan kecil yang konsisten. Misalnya antara lain menyapa satpam, merapikan gelas sendiri, mengucap nuhun tanpa menunda.
Mahasiswa perantau rata-rata datang dengan aksen daerah, membawa rumah mereka dalam kata-kata. Dan Bandung tidak pernah menghapus aksen itu. Bandung malah ikut menambah kosa kata mereka.
Ada hari-hari ketika kota memang terasa asing. Tugas menumpuk, rekening menipis, kabar dari rumah membuat dada sesak. Pada momen begitu, Bandung menawarkan jalan. Kota ini akan menenangkanmu dengan lampu-lampu yang tidak menghakimi.
Peta batin

Turisme emosional sejatinya adalah seni membuat peta batin. Kita menandai lokasi: “Di sini aku pernah berhasil.” “Di sini aku pernah belajar memaafkan.” “Di sini aku berhenti membandingkan.”
Festival musik, pameran, diskusi kecil di ruang komunitas, semuanya menambal retak-retak hati. Di panggung-panggung sederhana, keyakinan diperbaiki. Kota menjadi bengkel percaya diri.
Sementara itu, nilai kesundaan menyusup sebagai fondasi. Silih asah, silih asih, silih asuh bukan jargon museum, melainkan protokol hidup berjejaring.
Di sisi lain, Bandung juga sibuk menjual pesonanya. Heritage, kuliner, pemandangan, semua dikemas rapi. Mahasiswa perantau berdiri di persimpangan, antara menjadi penikmat sekaligus menjadi warga sementara. Dan mereka membayar dengan waktu.
Di laboratorium identitas itu, kesunyian adalah asisten dosen. Malam-malam menjelang subuh, tugas dan pikiran berkejar-kejaran. Kadang menang logika, kadang menang luka.
Nostalgia mulai tumbuh bahkan sebelum lulus. “Nanti kalau balik, kita makan di tempat yang sama, ya.” Janji-janji kecil menjadi semacam jangkar yang mengikat.
Ada pula pertarungan yang lebih senyap, antara keinginan pamer dan kebutuhan bermakna. Feed media sosial memanggil, namun dialog batin meminta kejujuran. Dan Bandung menyaksikan tanpa ikut campur.
Di ruang kelas, mereka belajar metodologi. Di jalan, mereka belajar empati. Dua-duanya penting. Yang kedua sering menyelamatkan yang pertama.
Ekonomi perasaan
Turisme emosional juga menghasilkan ekonomi perasaan. Toko-toko menjual kenangan, mulai dari kaos bergambar jalan hingga mug bergambar peta. Tapi, yang paling laku tetap cerita, yang dibagikan berkali-kali tanpa kehabisan stok.
Mahasiswa perantau awalnya datang sebagai pengunjung, pelan-pelan menjadi penghuni, lalu bersiap menjadi peziarah. Siklusnya sederhana namun dalam. Itulah ritme Bandung.
Pada hari wisuda, kota pun terasa melambat. Jalan masih macet, tapi hati serentak beres. Foto di gerbang kampus, pelukan, dan tawa yang mirip tangis.
Lalu koper-koper ditutup lagi. Kartu-kartu kos dikembalikan. Sisa-sisa jejak dititipkan ke bangku taman, ke dinding yang pernah jadi latar, ke awan yang menunggu hujan pertama.
Mereka pun pulang dengan gelar di tangan. Tetapi, yang paling bernilai adalah cara berdiri. Lebih tenang. Lebih rendah hati. Dan lebih tahu diri.
Dan Bandung? Bandung tetap menjadi kota yang pandai menyimpan rahasia. Ia membiarkan setiap orang merasa paling mengenalnya, padahal masing-masing memeluk Bandung yang berbeda.
Dan akhirnya, mereka paham bahwa belajar di Bandung adalah perjalanan akademik yang ditopang pariwisata batin. Kota ini menguji, merawat, dan melepas. Selebihnya, mereka menamainya sebagai rindu.***