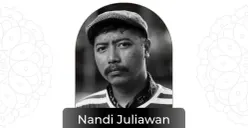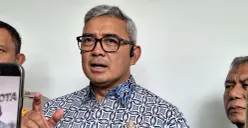“Bandung adalah tempat jiwa dan pikiranku ditempa.” Itulah ungkapan Presiden pertama RI, Soekarno, ungkapan yang menggambarkan betapa dalamnya ikatan antara Bung Karno dengan kota tempat menimba ilmu di Technische Hoogeschool (kini ITB). Bandung bagi Bung Karno bukan sekadar ruang kuliah, melainkan kawah candradimuka yang melahirkan dan membentuk pemimpin besar bangsa.
Hampir seabad setelah Soekarno mengucapkan kata-kata itu, Bandung tetap memegang peran penting sebagai magnet pendidikan nasional. Menurut survei GoodStats 2023, sebanyak 45 persen orang memilih Bandung sebagai kota utama untuk menempuh pendidikan.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat pun menunjukan bahwa pada tahun ajaran 2024, jumlah mahasiswa di Kota Bandung mencapai 856.961 mahasiswa yang tersebar di akademi, politeknik, institut, dan universitas, baik negeri maupun swasta. Angka tersebut menegaskan bahwa Bandung adalah episentrum pendidikan.
Daya tarik Bandung sebagai kota pendidikan sekaligus ekosistem pendidikan, terletak pada reputasi perguruan tinggi ternama seperti: ITB, Unpad, UPI, Telkom University, Universitas Pasundan, Maranatha hingga puluhan kampus lainnya.
Ditopang suasana kota yang nyaman dan fasilitas umum yang tertata, transportasi yang relatif memadai, biaya hidup yang terjangkau, serta ragam kuliner khas. Semua itu menjadikan Bandung istimewa di mata pelajar dan mahasiswa dari berbagai penjuru Indonesia.
Tantangan Pengembangan SDM
Meski penuh potensi, Bandung sebagai Kota Pendidikan dan Magnet Mahasiswa juga menghadapi sejumlah tantangan besar. Pertama konektivitas kurikulum dan riset dengan dunia kerja. Disrupsi digital dan kecerdasan buatan menuntut kampus-kampus di Bandung untuk adaptif, agar lulusannya relevan dengan kebutuhan industri dan masyarakat.
Kedua, fenomena brain drain. Bandung berisiko hanya menjadi “pencetak” SDM unggul tanpa mampu menjadi “pengguna”, karena banyak lulusan terbaik memilih berkarya di luar Bandung, bahkan di luar negeri.
Ketiga, ketimpangan akses pendidikan. Anak muda Bandung dengan potensi besar bisa tertinggal jika tidak mampu bersaing masuk kampus unggulan, di tengah ketatnya persaingan, serta tingginya biaya pendidikan jalur mandiri.
Dampak Ekonomi dan Sosial

Kehadiran ribuan mahasiswa menciptakan multiplier effect yang luar biasa. Ekosistem ekonomi baru tumbuh di sekitar kampus, seperti: kos-kosan, warung makan, kafe, percetakan, transportasi daring, hingga hiburan. Kehadiran mahasiswa tersebut juga mendorong tumbuhnya ekonomi kreatif, inkubator startup, komunitas teknologi, dan acara pendidikan (akademik) turut menggerakkan roda perekonomian kota.
Namun, ada sisi negatif. Tingginya permintaan hunian mendorong kenaikan harga sewa dan biaya hidup yang ikut membebani warga lokal.
Sementara kemacetan pun semakin parah terutama akses menuju kawasan kampus. Data TomTom Traffic Index 2024, menempatkan Bandung dalam peringkat 7 kota termacet di Asia dan ke 12 di dunia, dengan waktu tempuh rata-rata 32 menit 37 detik untuk menempuh jarak 10 km. Jika tidak dikelola dengan baik, dampak ekonomi justru akan berbalik menjadi ketimpangan sosial.
Secara sosial, Bandung ibarat miniatur Indonesia. Ratusan ribu mahasiswa dari berbagai daerah telah memperkaya keragaman budaya, bahasa, dan tradisi. Menjadikan Bandung sebagai ruang interaksi gagasan, asimilasi budaya, dan dialektika sosial.
Namun, dinamika tersebut berpotensi menimbulkan gesekan sosial. Gaya hidup mahasiswa seperti seperti nongkrong di kafe, hiburan malam, pola hidup digital, seringkali berbeda dengan tradisi masyarakat setempat. Kepadatan di kawasan kampus juga memicu masalah keamanan, parkir liar, hingga keramaian malam.
Jika tidak ditata, arus budaya modern berpotensi menekan identitas lokal Sunda. Bahasa Sunda semakin jarang terdengar di ruang publik, dan nilai-nilai tradisi melemah jika tidak diperkuat.
Solusi yang Perlu Didorong
Bandung harus tetap menjadi kota pendidikan yang sehat dan berdaya, maka sejumlah langkah strategis perlu ditempuh.
Mendorong kolaborasi kampus dengan pemerintah kota. Kurikulum dan riset kampus perlu selaras dengan kebutuhan lokal (ekonomi kreatif, teknologi, pendidikan guru), sekaligus menjawab agenda nasional (daya saing global, hilirisasi industri, transisi energi).
Menata kawasan pendidikan. Pemerintah perlu mengelola kawasan mahasiswa agar tidak menimbulkan kemacetan, kenaikan harga sewa, atau degradasi lingkungan sosial.
Menguatkan identitas lokal. Budaya Sunda bisa dijadikan bagian dari orientasi mahasiswa baru, agar tradisi lokal tetap hidup di tengah arus modernisasi.
Membangun integrasi sosial, mahasiswa diarahkan aktif pada kegiatan masyarakat, misalnya ronda malam atau kegiatan karang taruna, sehingga hubungan antara pendatang dan warga lokal lebih harmonis.
Bandung bukan hanya milik warganya, tetapi milik Indonesia. Bandung merupakan pusat pendidikan yang melahirkan dan memasok talenta terbaik untuk masa depan bangsa. Jika Bandung mampu mengelola tantangan dan meneguhkan perannya sebagai kota pendidikan, maka Bandung akan menjadi rujukan bagi kota pendidikan lain, seperti Yogyakarta, Malang, Surabaya, atau Makassar.
Dengan begitu, Bandung akan terus menjadi kebanggaan nasional sebagai motor penggerak pembangunan peradaban dan SDM unggul Indonesia. (*)