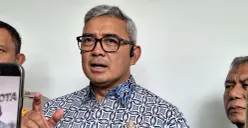Setiap sudut Bandung bercerita, dari trotoar hingga taman kota. Kota ini belajar, bermain, dan bahagia bersama warganya.
Setiap Minggu pagi, Jalan Dago dipenuhi ribuan orang. Ada yang berlari santai, bersepeda, berfoto, atau sekadar menikmati suasana Car Free Day. Sementara itu, di sudut lain kota, Taman Film yang pernah jadi ikon inovasi kota masih dikunjungi komunitas, meski tak sepopuler saat awal peresmiannya.
Di Alun-alun Bandung, keluarga berbondong-bondong melepas penat sambil membiarkan anak-anak berlarian di atas rumput sintetis yang menghijau. Semua itu memperlihatkan ruang publik Bandung hidup, berdenyut, dan menyatukan warganya.
Bagi banyak kota besar di Indonesia, ruang publik kerap menjadi barang mewah. Pertumbuhan pusat perbelanjaan, kafe, dan gedung komersial sering kali menggeser hak warga atas ruang terbuka. Bandung, meski bukan tanpa masalah, mencoba memberi wajah lain. Sejak awal 2010-an, pemerintah kota serius membenahi ruang publik: dari membangun taman tematik seperti Taman Fotografi, Taman Lansia, hingga revitalisasi alun-alun kota.
Upaya ini tidak hanya bersifat fisik. Ada gagasan yang lebih besar, dimana kota harus menyediakan ruang inklusif, gratis, dan terbuka bagi semua warganya. Ruang publik menjadi penyeimbang dari derasnya arus komersialisasi, sekaligus menegaskan identitas unik Bandung.
Ruang Publik, Tempat Belajar, Bercengkrama, dan Bahagia
Bandung dikenal sebagai kota pendidikan dan kota kreatif. Ruang publik pun seperti: trotoar dengan “Batu Meriam”, taman, dan jalanan kota menjadi tempat belajar.
Komunitas skateboard memanfaatkan jalur pedestrian Dago, anak-anak yang belajar membaca di pojok literasi, warga berkumpul untuk diskusi atau kelas yoga gratis, seniman mural mengubah tembok kosong menjadi kanvas, musisi jalanan menjadikan Car Free Day sebagai panggungnya, dan “comjurig Bandung" komunitas lokal di jalan Asia Afrika yang menampilkan parodi hantu yang kocak di siang hari.
Ruang publik di Bandung bukan sekadar tempat melepas penat, melainkan menjadi kelas terbuka, di mana siapa pun bisa belajar dan berekspresi. Fenomena ini menunjukkan nilai lebih ruang publik dalam membentuk karakter kota dan warganya.
Seperti penggalan lirik lagu Maripi yang pernah dipopulerkan oleh Kang Darso, “…Engklak engklakan Maripi lucu pisan, Barudak urang Ngariung di buruan…”, ruang publik (buruan) menjadi simbol kebahagiaan dan akses menuju pengalaman kolektif yang menyenangkan bagi warga.

Meski begitu, tidak semua ruang publik Bandung berjalan sesuai harapan. Beberapa taman tematik yang sempat populer kini kurang terawat. Tantangan klasik seperti sampah, keamanan, dan fasilitas bagi penyandang disabilitas masih menghantui. Selain itu, ruang publik kerap “berkompetisi” dengan kepentingan komersial. Di banyak sudut, ruang publik dikepung iklan, kafe, dan parkir liar.
Isu inklusivitas juga menjadi sorotan. Apakah semua warga merasa memiliki ruang publik, atau hanya kelompok tertentu? Sosiolog kota menyebut ruang publik sebagai “cermin demokrasi”. Di sanalah warga hadir tanpa syarat, mengekspresikan diri, dan berinteraksi lintas batas. Bandung memberi contoh bahwa ruang publik menjadi arena demokrasi kota. Anak muda bebas berkarya, komunitas bisa mengadakan acara, dan keluarga dapat menikmati kota tanpa merasa asing. Ruang publik menjadi simbol kesetaraan.
Di tengah kepadatan dan era digital, Bandung berpeluang besar mengembangkan ruang publik sebagai laboratorium kota pintar yang humanis. Wifi gratis di taman kota dan Cipol Arena 3: Micro Food Forest di kelurahan Darwati adalah sekian contoh komitmen Bandung yang tidak hanya fokus pada aspek digital, tetapi juga mempertahankan kebutuhan sosial dan lingkungan, menjadikan ruang publik sebagai bagian integral dari konsep kota pintar yang humanis.
Bayangkan taman hijau yang interaktif, dilengkapi Wi-Fi, sensor lingkungan, hingga fasilitas edukatif. Ruang publik bisa menjadi perpaduan antara interaksi sosial tradisional dan kebutuhan digital generasi muda.
Baca Juga: Selebritisasi Politik dan Kebudayaan di Bandung
Ruang publik adalah napas kota, tempat belajar, bermain, berkreasi, dan membangun solidaritas. Bandung sudah membuktikan potensinya, tapi pekerjaan belum selesai. Perawatan, pengembangan, dan inklusivitas harus terus dijaga agar kota tercinta ini tetap hidup dan bahagia bagi generasi mendatang.
Pertanyaan terakhir yang selalu menggantung, Apakah kita, sebagai warga, siap merawat ruang publik Bandung agar denyut kehidupan kota ini tidak pernah padam? (*)