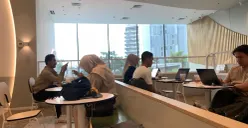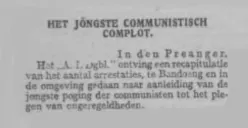Di banyak tempat, termasuk di Bandung, sungai adalah nadi kehidupan. Cikapundung, Citarum, dan puluhan anak sungainya bukan hanya aliran air, tapi juga aliran sejarah, budaya, dan spiritualitas.
Dalam kosmologi masyarakat Sunda, air adalah anugerah dan sungai adalah perpanjangan tangan para leluhur. Para leluhur kita meyakini sungai bukan sekadar tempat mandi atau mencuci, tapi juga ruang pertemuan sosial, sumber penghidupan, bahkan tempat berkontemplasi.
Namun, jejak sakral itu kiwari mulai terhapus. Betapa tidak. Dalam ingatan generasi modern, sungai cenderung identik dengan bau, kotoran, dan limbah berbahaya.
Dan hal tersebut bukan sekadar terkait perubahan fisik, tapi juga terkait perubahan batin kolektif kita terhadap alam. Perubahan itu tak datang ujug-ujug dan seketika. Ia lahir dari logika pembangunan yang selama ini telah memarjinalkan peran air.
Kota Bandung yang dulu dibangun dengan memperhatikan topografi dan aliran sungai, kini bisa dibilang berkembang serampangan. Bahkan, melupakan hukum air.
Sungai-sungai yang dulu menjadi nadi kehidupan, kini menjadi tempat sampah raksasa. Limbah domestik, limbah industri, dan aneka macam sampah mengalir tanpa ampun ke dalam tubuh air yang dulu diyakini suci. Nadi kehidupan itu kini tercemar. Dan perlahan, ia menjadi noda peradaban.
Citarum, salah satu sungai utama yang mengaliri bukan saja sebagian Bandung Raya, tetapi juga sebagian Jawa Barat, pernah dijuluki sebagai salah satu sungai terkotor di dunia. Ironisnya, ia adalah sumber air bagi jutaan warga.
Dalam tubuh Citarum, termuat ironi ekologis maupun sosial. Sungai yang seharusnya menumbu kehidupan justru melahirkan penyakit. Limbah dari pabrik-pabrik tekstil, limbah rumah tangga, dan peternakan membunuh biota air dan harapan warga.
Program Citarum Harum pun digulirkan, melibatkan tentara, relawan, dan pemerintah daerah. Tapi, problem dasarnya ternyata lebih dalam. Kita telah kehilangan relasi spiritual dengan sungai.
Padahal, relasi spiritual ini penting. Dalam budaya lokal, sungai bukan hanya bagian dari lanskap, tapi juga entitas hidup. Mengotori sungai sama dengan mencederai tubuh sendiri.
Sayangnya, kota modern tak lagi mengenal bahasa kesakralan. Dalam tata kota kita, sungai direken hanya drainase. Adapun dalam rencana pembangunan kita, sungai tak jarang hanya dianggap lahan kosong yang bisa ditutup, dijadikan jalan, bahkan ditimbun.
Baca Juga: Partisipasi Semesta Wujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua
Sementara itu, di banyak kota besar dunia, sungai direstorasi sebagai bagian dari ruang hidup bersama. Di Seoul, Korea Selatan, Sungai Cheonggye direvitalisasi, mengubah saluran air yang tertutup beton menjadi ruang publik yang hidup.
Sementara di Bandung dan sekitarnya, banyak anak sungai menghilang dari peta lantaran tertutup bangunan, diurug tanah, dan dilupakan dalam perencanaan pembangunan. Padahal, secara ekologis, sungai adalah pengatur suhu mikro. Ia penjaga kelembaban dan pengendali banjir alami.
Maka, ketika kita menterlantarkan sungai, kita justru membuka pintu petaka. Banjir berulang yang mengepung sejumlah wilayah Bandung Raya bukan semata soal hujan yang turun deras, tapi soal sungai yang tak lagi bisa bernapas. Saluran sungai menyempit, alirannya terhambat, tubuhnya penuh luka.
Padahal, sungai juga mengandung memori kolektif. Banyak warga Bandung yang lahir dan tumbuh bersama aliran Cikapundung, misalnya, bermain di tepiannya, memancing ikan di pagi hari, bahkan jatuh cinta di dermaganya. Tapi, semua itu tinggal cerita indah kakek-buyut kita.
Ketika sungai berubah menjadi got besar, kita kehilangan bukan hanya fungsi ekologis, tapi juga identitas budaya. Sungai tak bisa dibersihkan hanya dengan dana APBD atau program berslogan indah. Ia butuh pula perubahan paradigma kita, yakni dari melihat air sebagai komoditas menjadi air sebagai entitas hidup.

Perubahan paradigma ini harus dimulai dari sektor pendidikan. Sekolah-sekolah bisa menjadikan sungai sebagai laboratorium hidup, tempat belajar ekosistem, sejarah, bahkan sastra mupun seni musik.
Kampus dan perguruan tinggi juga dapat turut berperan. Kajian interdisipliner soal urbanisasi, ekologi, dan air bisa menghasilkan solusi berbasis lokal yang membumi.
Tapi yang lebih penting dari semua itu adalah kesadaran kolektif warga. Tanpa partisipasi publik, sungai akan terus terasing.
Kita bersyukur komunitas warga yang peduli pada sungai-sungai di Bandung kini mulai bermunculan. Mereka melakukan bersih-bersih sungai, menanam pohon di bantaran, dan membuat kegiatan seni di tepian sungai.
Inisiatif seperti ini perlu diperkuat, diperluas, dan dimasifkan. Karena peradaban sejati lahir bukan dari pencakar langit, tapi dari bagaimana kita memperlakukan sungai.
Kota yang sehat bukan hanya kota tanpa macet, tapi juga kota yang bisa mendengar suara air. Bandung punya peluang besar untuk memperbaiki relasi sungai dan warganya.
Letaknya yang strategis, sejarahnya yang kaya, dan kreativitas warganya adalah modal sosial yang besar. Tapi, peluang itu akan sia-sia jika kota ini terus membangun dengan logika beton dan aspal, bukan dengan logika air dan kehidupan.
Baca Juga: Serunya Pacu Kuda di Tegallega
Revitalisasi sungai tidak harus mahal. Dapat dimulai dari membuka akses publik ke sungai, membuat jalur hijau, dan melibatkan warga sebagai pengelola.
Kearifan lokal Sunda bisa menjadi landasan. Konsep cai nu kudu dihormat adalah etika ekologis yang relevan di era krisis iklim kiwari.
Sungai bukan halaman belakang kota. Ia adalah wajah kota. Kota yang membelakangi sungai pada akhirnya membelakangi kehidupan itu sendiri.
Sungai-sungai di Bandung masih mengalir, meski tersengal. Mereka sedang menunggu kita kembali, bukan sebagai penakluk, tapi sebagai sahabat sejati.
Bandung sama sekali bukan kota mati. Tapi, ia bisa menjadi kota yang membunuh dirinya sendiri jika sungai-sungai di kota ini terus diperlakukan sebagai musuh. Oleh sebab itu, mari kita menata ulang relasi kita dengan sungai.
Pada akhirnya, sungai adalah cermin. Jika ia kotor, kita pun sedang memandangi wajah kita sendiri yang kian tercemar. Maka, jangan biarkan cermin itu kotor dan menjadi noda peradaban. (*)